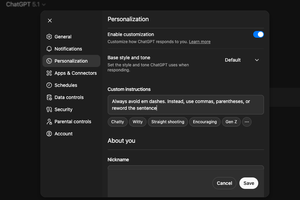Korupsi dan konflik
Krisis kehutanan Indonesia juga tidak lepas dari pusaran korupsi, konflik agraria, dan ketidakadilan ekologis terhadap masyarakat adat.
Korupsi di sektor kehutanan kerap terjadi melalui kolusi antara pejabat, politisi, dan pengusaha.
Studi Paul Kenny dan Eve Warburton (2020) menemukan 33,2 persen pebisnis di sembilan provinsi mengalami pungutan liar, sedangkan 35,7 persen menganggap praktik itu biasa saja. Sektor kehutanan, konstruksi, dan pertambangan menjadi lahan basah untuk praktik ini.
Kajian Jacqui Baker (2020) di Pelalawan, Riau, menelusuri jaringan korupsi kehutanan yang melibatkan lebih dari 200 simpul, mulai dari dinas kehutanan, industri pulp, hingga politisi.
Walaupun jumlah pejabat yang terlibat tidak banyak, pengaruh mereka sangat besar karena menguasai sumber daya lahan dan kebijakan. Konflik kepentingan membuat pencegahan korupsi berjalan setengah hati.
Kasus Tesso Nilo adalah salah satu contoh bagaimana kebijakan diselewengkan demi kepentingan sempit. Penerbitan SHM di kawasan taman nasional menegaskan lemahnya pengawasan.
Bayangkan, Indonesia hanya punya 7.000 polisi kehutanan (polhut) untuk mengawasi kawasan seluas lebih dari 120 juta hektar.
Artinya, satu polhut harus mengawasi rata-rata 17.000–18.000 hektar. Padahal idealnya, satu petugas hanya memantau 500–1.000 hektar agar bisa bekerja efektif.
UU Nomor 23 Tahun 2014 pun membuat fungsi pengawasan sebagian besar ditarik ke pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten nyaris tidak berperan, kecuali untuk taman hutan raya.
Rentang kendali yang terlalu jauh menyebabkan banyak kejadian di lapangan luput dari pantauan.
Perlu reformasi serius
Mereformasi tata kelola kehutanan tidak bisa ditunda lagi. Revisi UU 41/1999 yang sedang berproses di DPR sebaiknya tidak hanya soal prosedur, tetapi fokus pada pembenahan pengawasan, penguatan fungsi ekologis hutan, dan tata kelola yang adil.
Kebijakan kehutanan ke depan juga perlu diikuti dengan menambah jumlah polhut, meningkatkan kapasitas teknologi, serta mengembalikan sebagian fungsi pengawasan ke pemerintah daerah agar lebih dekat dengan masyarakat sekitar hutan.
Baca juga: Serial Squid Game Berakhir, Apa Keserakahan Tak Bertepi Terus Eksis di Negeri Ini?
Selain itu, harus ada larangan tegas penambangan terbuka di kawasan hutan lindung dan penghentian praktik legalisasi sawit di kawasan konservasi.
Pemerintah perlu melakukan audit total terhadap sertifikat tanah di kawasan hutan, serta menegakkan transparansi dalam mekanisme inventarisasi kawasan hutan berbasis partisipasi publik.
Restorasi kawasan yang sudah rusak pun tidak boleh bergantung hanya pada investor. Model padat karya berbasis komunitas lokal perlu diprioritaskan, sekaligus menghentikan ekspansi industri ekstraktif di kawasan lindung dan konservasi.
Kasus Tesso Nilo hanyalah cermin dari bobroknya tata kelola kehutanan kita. Jika tidak ada perubahan mendasar, krisis serupa akan terus berulang, menjerumuskan Indonesia ke pusaran bencana ekologis yang lebih besar.
Momentum pengembalian 1,019 juta hektare kawasan hutan oleh Satgas PKH seharusnya dijadikan titik balik untuk memulihkan fungsi hutan sebagai penyokong kehidupan, bukan sekadar lahan produksi jangka pendek.
Jika reformasi gagal, generasi mendatang hanya akan mewarisi tanah kritis, banjir, kekeringan, krisis air bersih, dan kerentanan pangan. Jangan sampai itu terjadi.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya