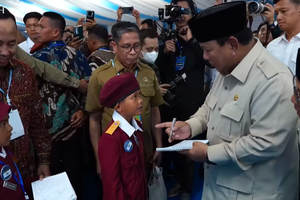Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

KONFERENSI Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, kembali membuka perdebatan tentang ke mana arah politik iklim global bergerak. Pada satu sisi, forum ini dipromosikan sebagai ruang untuk memperkuat ambisi pengurangan emisi. Namun pada sisi lain, semakin jelas bahwa mekanisme pasar karbon yang terus dilegalkan justru memperlihatkan wajah lain COP: ruang yang semakin dikuasai negara-korporasi, bukan masyarakat yang selama ini menjaga hutan dan biodiversitas.
Ambisi Perdagangan Karbon dan Ekspansi Kepentingan Negara-Korporasi
Delegasi Indonesia datang ke COP30 dengan target ambisius: transaksi perdagangan karbon hingga Rp16 triliun. Target itu berangkat dari rencana menjual 90 juta ton CO2 dalam bentuk kredit karbon, baik dari sektor kehutanan, kelautan, maupun teknologi. Delegasi yang berjumlah lebih dari seratus negosiator disiapkan untuk mempertemukan penjual dan pembeli, serta membangun kesepakatan bilateral dengan berbagai lembaga dan perusahaan.
Angka Rp16 triliun sering digambarkan sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk memasuki ekonomi hijau. Namun pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apakah manfaat ekonomi ini benar-benar akan mengalir ke masyarakat adat, petani kecil, dan penjaga hutan yang menghasilkan jasa ekosistem? Ataukah justru menjadi peluang baru bagi negara dan korporasi memperluas kontrol atas ruang hidup masyarakat?
Para ekonom lingkungan mengingatkan bahwa pasar karbon bekerja berdasarkan logika komodifikasi. Hutan, udara, dan laut diperlakukan sebagai aset finansial. Dalam kerangka kapitalisme hijau, nilai karbon dihitung melalui sertifikasi, verifikasi, dan transaksi, sementara aspek non-ekonomi—seperti nilai kultural, spiritual, dan relasi ekologis—tidak diperhitungkan.
Di sinilah problem mendasar muncul: apakah mekanisme ini akan mendorong pengurangan emisi yang nyata, atau sekadar menjadi ladang baru untuk akumulasi kapital?
Baca juga: COP30: Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Fraud Perdagangan Karbon
Ketidakadilan Struktural dan Luka bagi Masyarakat Adat
Di tengah gaung transaksi karbon, suara masyarakat adat justru menjadi yang paling ditinggalkan. Di Brasil, komunitas adat seperti Munduruku melakukan aksi protes selama COP30, menuding penyelenggaraan konferensi telah mengecilkan peran mereka dalam mengambil keputusan tentang lahan dan wilayah adat.
Kejadian serupa sering terjadi di Asia Tenggara, Afrika, hingga Pasifik, di mana proyek-proyek karbon memasuki wilayah adat tanpa konsultasi yang memadai. Para peneliti hak asasi manusia mencatat bahwa ketika karbon dijadikan komoditas, wilayah adat sering berubah status menjadi “aset karbon” yang membutuhkan pengawasan eksternal. Hal ini membuka peluang kontrak jangka panjang yang membatasi akses masyarakat terhadap hutan, mengubah praktik adat, bahkan menyebabkan konflik atas kontrol lahan.
Di sejumlah negara, proyek offset juga terbukti hanya mengalirkan sebagian kecil pendapatan kepada komunitas lokal, sementara lembaga perantara dan perusahaan mengambil keuntungan terbesar.
Risiko ini semakin besar ketika negara mengejar target transaksi besar seperti di COP30. Masyarakat adat berpotensi tidak mendapatkan posisi sebagai pengambil keputusan, hanya sebagai objek proyek yang dipantau dari luar. Padahal, dalam banyak studi, justru wilayah adat yang memiliki tingkat deforestasi terendah dan keutuhan ekologi tertinggi. Dengan kata lain, mereka menjaga hutan bukan karena logika pasar, melainkan relasi budaya yang panjang dengan alam.
Baca juga: Fokus Perdagangan Karbon, Misi RI di COP 30 Dinilai Terlalu Jualan
Kualitas Kredit Karbon dan Tantangan Keberlanjutan
Selain persoalan keadilan, masalah kualitas kredit karbon juga menjadi sorotan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian proyek offset memiliki integritas lingkungan yang rendah. Masalah seperti penghitungan ganda, klaim penurunan emisi yang tidak dapat diverifikasi, hingga pengukuran baseline yang keliru menjadi temuan umum.
Sejumlah laporan lembaga independen menyebut pasar karbon global menghadapi “krisis kredibilitas”, terutama karena tidak semua kredit benar-benar mewakili pengurangan emisi yang nyata.
Ketergantungan negara terhadap offset juga dapat melemahkan transformasi sektor energi. Alih-alih menurunkan emisi dari sumbernya, negara atau korporasi dapat membeli kredit untuk mengompensasi emisi yang terus dilepaskan. Mekanisme ini, menurut para ahli, menciptakan ilusi progres, padahal secara global emisi tetap tinggi. Bahkan tuan rumah COP30, Brasil, memperingatkan agar negara-negara tidak menjadikan kredit karbon sebagai jalan pintas yang menunda transisi energi bersih.
Di Indonesia, tantangan juga muncul dari minimnya mekanisme transparansi publik, lemahnya pengawasan lapangan, serta belum kuatnya perlindungan hak atas tanah di wilayah adat. Tanpa pembenahan ini, skema perdagangan karbon berpotensi menjadi instrumen yang memperkuat korporasi dan elite politik, bukan alat pengurangan emisi yang berkeadilan.
Pada akhirnya, COP30 memberi kita cermin: apakah Indonesia ingin berada dalam jalur kapitalisme karbon yang menguntungkan negara-korporasi, atau membangun jalan lain yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama keadilan iklim? Keputusan itu tidak hanya menentukan arah ekonomi hijau, tetapi juga masa depan hutan, laut, dan komunitas yang telah menjaga ekosistem jauh sebelum karbon dihitung sebagai komoditas finansial.
Baca juga: Tak Niat Atasi Krisis Iklim, Pemerintah Bahas Perdagangan Karbon untuk Cari Cuan
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya