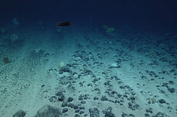Bukan "Greenflation", tapi "Climateflation" dan "Fossilflation" Lebih Mendesak Ditangani

Kita tahu, saat mengadopsi proses produksi yang lebih ramah lingkungan, sebagian besar teknologi ramah lingkungan sangat bergantung pada logam dan mineral seperti tembaga, litium, dan kobalt, terutama pada masa transisi.
Kendaraan listrik, misalnya, menggunakan mineral enam kali lebih banyak dibandingkan kendaraan konvensional. Pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai membutuhkan tembaga tujuh kali lipat dibandingkan pembangkit listrik tenaga gas.
Terlepas dari jalur dekarbonisasi yang kita lakukan, teknologi ramah lingkungan akan menjadi pendorong terbesar permintaan logam dan mineral pada masa depan. Namun saat permintaan energi hijau terus melaju, pasokannya akan kian terbatas.
Sama seperti migas, pengembangan tambang logam baru membutuhkan waktu bertahun-tahun, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pasokan permintaan dan kenaikan harga.
Harga nikel dan litium, misalnya, pernah meroket tahun 2020. Namun, harga keduanya mulai turun sejak akhir 2023.
Artinya, harga komoditas logam untuk keperluan transisi energi masih fluktuatif, tidak berada dalam tren naik seperti yang dikhawatirkan.
Namun ke depan, kita perlu siap-siap, karena hal ini menimbulkan paradoks yang krusial, semakin cepat kita melakukan transisi menuju ekonomi ramah lingkungan, maka biayanya akan semakin mahal dalam jangka pendek.
Meskipun greenflation belum berdampak signifikan terhadap harga konsumen saat ini, hal ini akan memberikan tekanan pada produk yang lebih beragam karena semakin banyak industri yang mengadopsi teknologi rendah emisi.
Hanya saja, kita perlu lebih cepat sigap mengantisipasi inflasi akibat perubahan iklim (climateflation) dan inflasi bakan bakar fosil (fossilflation). Jika tidak terkendali, maka dua jenis inflasi energi ini akan sangat mengganggu perekonomian dalam jangka pendek.
Keberhasilan kita mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar fosil dan inflasi akibat perubahan iklim dan serta mengurangi dampak bencana akibat perubahan iklim akan membantu kita mengendalikan inflasi hijau pada masa depan.
Transmisinya adalah mengendalikan climateflation dan fossilflation terlebih dulu, baru greenflation akan ikut terkendali, jangan terbalik.
Dengan kata lain, pemerintah perlu lebih fokus menangani jenis inflasi yang memang sedang kita hadapi dan lebih urgen untuk segera dicarikan solusinya seperti inflasi pangan, beras khususnya yang masih bertahan tinggi.
Rencana impor beras hanya sekadar untuk menstabilkan pasokan/cadangan, bukan untuk menstabilkan harga di tingkat penjual dan pembeli.
Maksudnya, mari kita fokus pada inflasi di depan mata (climateflation dan fossilflation) yang sangat berdampak pada masyarakat yang paling rentan. Serta tidak lupa mengantisipasi inflasi hijau (greenflation) saat transisi energi kian masif ke depan.
Mengenali tantangan dan peluang dari inflasi energi baru ini tentu sangatlah penting. Mempercepat penerapan energi terbarukan sekaligus melindungi populasi rentan adalah jalan menuju masa depan yang berkelanjutan dan aman.
Seperti yang disebutkan para pakar, merangkul energi terbarukan sebagai energi kebebasan bukan hanya keterpaksaan.
Namun di lain sisi, energi terbarukan juga strategis, membuka jalan bagi Indonesia yang lebih berketahanan dan mandiri, dan tentu saja, dunia lebih baik untuk semua.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya