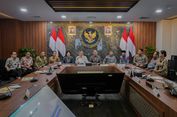Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Oleh Endi Aulia Garadian*
KOMPAS.com - Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dalam Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index, GFSI), dengan skor 60,2/100.
Indeks tersebut mencatat akses masyarakat terhadap pangan tergolong baik, namun ketersediaan dan keberlanjutan pangan masih menjadi tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses petani terhadap permodalan.
Hasil Survei Ekonomi Pertanian 2024 menunjukkan 81,52 persen petani tidak memiliki akses kredit, terutama karena prosedur yang rumit. Sementara itu, dukungan negara masih terbatas, baik dari sisi pendanaan maupun pengembangan riset-riset pertanian.
Di tengah ketidakpastian ini, lembaga filantropi hadir mengisi celah tersebut dan menyediakan solusi alternatif untuk mendukung sektor pangan di Indonesia. Meski, mereka juga menghadapi tantangan dalam keberlanjutan seperti keterbatasan pendanaan jangka panjang hingga kurangnya dukungan regulasi.
Peran filantropi dalam sektor pangan
Lembaga filantropi punya peran penting dalam memperkuat negara dan pemerintahan. Di Amerika Serikat, lembaga-lembaga filantropi memiliki posisi kuat, bahkan filantropi korporasi sering kali menjadi “pelaksana” program-program pemerintah (third party government).
Di Indonesia, lembaga filantropi lebih banyak bergerak mandiri. Sektor ini didominasi oleh lembaga filantropi berbasis keagamaan, terutama Islam, yang aktif di berbagai sektor, salah satunya pangan.
Sejarah menunjukkan lembaga amal banyak berperan dalam menangani krisis pangan. Misalnya, saat Great Depression pada tahun 1930-an melanda Pulau Jawa. Kala itu, lonjakan kemiskinan terjadi di mana-mana, terutama di perkotaan dan memunculkan golongan yang disebut dengan kaum miskin perkotaan (urban poor). Sementara itu, pemerintah tidak memiliki jaring pengaman sosial yang memadai.
Organisasi Islam seperti Muhammadiyah—yang merupakan pelopor pengelolaan filantropi terstruktur—turun tangan menyalurkan bantuan sosial, termasuk pangan. Meski saat itu, bantuan masih diberikan dengan prinsip selektivitas alias masih memilah-milah ‘kaum miskin’ penerima bantuan.
Hari-hari ini, lembaga filantropi Islam terus berkembang semakin banyak dan juga kian inklusif dengan praktik-praktik yang mengedepankan keadilan sosial. Kerangka ini mendefinisikan aksi-aksi derma tidak hanya sebatas pemberian bantuan langsung, tetapi memberikan dukungan jangka panjang untuk menciptkan masyarakat yang berdaya, terutama di sektor pangan.
Berbagai upaya yang dilakukan lembaga filantropi dalam meningkatkan ketahanan pangan di antaranya dengan mendukung petani melalui pendampingan teknis, hibah usaha tani, serta investasi dalam infrastruktur pertanian. Pendekatan dilakukan dengan berbasis komunitas serta modernisasi tata kelola yang menyasar akar masyarakat di pedesaan.
Salah satu contohnya adalah pemberdayaan ketahanan pangan yang dilakukan Dompet Dhuafa lewat program pertanian organik dan peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Program Desa Tani Dompet Dhuafa di Jawa Barat misalnya, mengubah lahan kurang produktif menjadi pertanian bernilai ekonomi tinggi. Penerima manfaat program ini adalah petani miskin. Mereka diberikan modal kerja berupa lahan, bibit, dan bahan produksi lainnya, serta pendampingan intensif.
Diinisiasi sejak 2018, program Desa Tani ini kini telah berhasil meningkatkan pendapatan petani menjadi rata-rata Rp 2,7 juta per bulan, dari yang sebelumnya tidak menentu. Pada tahun kedua program, kelompok tani berkembang menjadi kelembagaan Koperasi Agronative yang dikelola sendiri oleh para petani penerima manfaat.
Selain Desa Tani, ada juga program Desa Kopi Solok Sirukam di Sumatera Barat dan Desa Kopi Sinjai di Sulawesi Selatan. Dompet Dhuafa memberikan bantuan modal untuk pupuk, hingga pendampingan budidaya dan pengolahan kopi menjadi biji kopi (greenbeans), serta pendampingan pemasaran produk untuk meningkatkan pendapatan petani di sana.
Contoh lain adalah Badan Usaha Milik Masyarakat-Desa Berdaya (BUMMas-DesBer) yang diinisiasi oleh Rumah Zakat. Program ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa lewat pertanian berkelanjutan. Rumah Zakat mendampingi masyarakat untuk memanfaatkan potensi lahan yang tersedia dengan menanam sayur-mayur dan membuat pupuk organik secara mandiri.
Apa yang mereka lakukan adalah upaya memandirikan perekonomian masyarakat desa dan secara bersamaan memperkuat ketahanan pangan. Sekali dayung, dua-tiga pulau terlampaui. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan modernisasi tata kelola, filantropi tidak sekadar memberikan bantuan langsung, tetapi juga berkontribusi mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.
Baca juga: Agroforestri Intensif Dinilai Jadi Solusi Ketahanan Pangan dan Krisis Iklim
Program-program semacam ini membantu membangun sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga filantropi dapat menjadi katalis dalam memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.
Tantangan keberlanjutan program
Meski menjanjikan, lembaga-lembaga filantropi juga menghadapi tantangan keberlanjutan program, terutama terkait pendanaan program jangka panjang.
Di Indonesia, pemberi zakat (muz akki) atau donatur masih cenderung tergerak untuk memberikan bantuan langsung (relief), ketimbang mendukung inisiatif yang berorientasi jangka panjang.
Survei Nasional tentang Zakat yang pernah dilakukan oleh para peneliti dari Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta pada 2004-2005, menujukkan bahwa 93 persen pemberi zakat lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada penerima (mustahik) zakat daripada melalui lembaga filantropi. Setelah itu, belum ada lagi survei nasional yang memotret tradisi masyarakat berderma. Baznas, misalnya saja, lebih senang dengan survei dana yang terkumpul daripada mencari tahu alasan dibalik kenapa orang mau menunaikan ziswaf.
Meski bantuan langsung tetap dibutuhkan, pola ini perlu diubah agar filantropi bisa berperan lebih besar dalam berbagai masalah ketimpangan struktural melalui program berkelanjutan.
Selain dana dari masyarakat, filantropi korporasi atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) juga seharusnya bisa menjadi solusi mengatasi keterbatasan pendanaan ini. Di Amerika Serikat, lagi-lagi, perusahaan kerap melakukan aksi derma—tak hanya dalam bentuk dukungan finansial, tapi juga dukungan sumber daya, atau layanan kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.
Di Indonesia, beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan praktik serupa. Sebagian ada yang memilih menyalurkan dana CSR lewat lembaga amal internal, ada pula yang mengembangkan program-program sosial sendiri yang dianggap sesuai dengan nilai perusahaan. Jika korporasi-korporasi ini menjalin kerja sama dengan lembaga filantropi, jangkauan manfaatnya tentu bisa semakin luas.
Tantangan lainnya adalah soal kerangka regulasi. Undang-undang yang mengatur soal filantropi di Indonesia sudah usang, masih merujuk pada Undang-Undang (UU) No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Aturan lawas ini sudah ketinggalan zaman dan belum mengakomodasi perkembangan terkini, seperti filantropi digital.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Sumbangan yang kini digodok parlemen pun belum jelas ujungnya, padahal regulasi yang lebih adaptif sangat dibutuhkan saat ini.
Lembaga filantropi telah membuktikan bahwa mereka bisa menjadi lebih dari sekadar penyedia bantuan; tapi juga katalis perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan negara, khususnya dalam hal keberpihakan regulasi, amat diperlukan untuk mendukung kerja-kerja mereka. Begitu pula kemitraan dengan sektor korporasi, dapat memperluas dampak program yang tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Maluku Punya Lahan Sagu 36.462 Hektare, Bisa Dukung ketahanan Pangan
*Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya