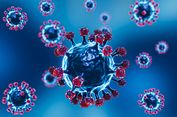Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

BANJIR dan longsor secara berulang di sejumlah wilayah Sumatera dan Jawa Barat dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan satu kenyataan yang kian sulit dibantah: bencana di Indonesia bukan lagi peristiwa luar biasa, melainkan pola yang berulang. Setiap musim hujan, cerita yang sama hadir dengan lokasi yang berbeda.
Hujan deras kerap dijadikan penjelasan utama, seolah alam sepenuhnya bertanggung jawab. Padahal, hujan hanyalah pemicu. Akar persoalannya terletak pada kegagalan berlapis dalam pengelolaan ruang hidup.
Di Sumatera, banjir terjadi di wilayah yang dahulu dikenal sebagai daerah resapan dan penyangga ekologi. Sungai meluap, permukiman terendam, aktivitas ekonomi lumpuh, dan warga kembali mengungsi. Di Jawa Barat, longsor di kawasan perbukitan menelan korban jiwa, merusak rumah, dan memutus akses desa.
Bencana alam sedang terjadi di berbagai wilayah berbeda akibat dua pemicu berbeda yaitu banjir dan longsor, tetapi memiliki satu benang merah yang sama: pembangunan telah melampaui daya dukung alam dan mengabaikan batas-batas sosial-ekologis.
Baca juga: Setelah Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Bencana Sumatera, Apa Selanjutnya?
Dua lapis kelemahan
Jika ditelisik lebih dalam, kelemahan setidaknya terjadi pada dua lapis sekaligus. Pertama, melemahnya adaptasi berbasis kearifan lokal. Kedua, lemahnya konsistensi kebijakan tata ruang yang seharusnya bersifat tegas dan dijakankan secara konsisten.
Masyarakat di Sumatera, Jawa Barat, dan berbagai wilayah rawan bencana di Indonesia sejatinya tidak asing dengan risiko alam. Pengetahuan tentang air, tanah, dan kontur telah diwariskan lintas generasi. Rumah dibangun mengikuti topografi, lereng dijaga dengan vegetasi tertentu, dan alur air dipahami sebagai bagian dari kehidupan, bukan ancaman yang harus disingkirkan.
Dalam perspektif antropologi ekologi, adaptasi merupakan sebuah konsep kultural yang tercermin dalam kearifan masyarakat terhadap alam. Pengetahuan ini lahir dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan lanskap yang rapuh.
Namun, adaptasi berbasis kearifan lokal memiliki batas. Ia bekerja pada skala komunitas dan pada lanskap yang relatif stabil. Ketika tekanan eksternal datang bertubi-tubi berupa alih fungsi lahan masif, ekspansi perkebunan, kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur maka pengetahuan lokal kehilangan ruang untuk bekerja.
Sungai yang dahulu “dimaknai” sebagai penanda batas ekologis dan tatanan hidup masyarakat, kini sering direduksi menjadi batas fisik dan administratif yang dapat ditimbun dan diratakan atas nama pembangunan. Lereng yang semula dijaga berubah menjadi lokasi bangunan permanen. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tetap beradaptasi, tetapi adaptasi itu bersifat defensif, bukan preventif. Di sinilah kebijakan tata ruang seharusnya hadir sebagai penyangga utama.
Sayangnya, di banyak wilayah, rencana tata ruang sering berhenti sebagai dokumen administratif. Peta kawasan rawan banjir dan longsor tersedia, tetapi daya paksa untuk menegakkannya lemah. Ketika kepentingan ekonomi dan investasi datang, batas ekologis menjadi lentur. Risiko tidak dihapus, melainkan dipindahkan dan hampir selalu menimpa kelompok yang paling rentan.
Longsor di Jawa Barat menunjukkan bagaimana pembangunan di kawasan perbukitan terus berlangsung meskipun tanda-tanda kerentanan telah berulang kali muncul. Banjir di Sumatera memperlihatkan bagaimana daerah aliran sungai kehilangan fungsi ekologisnya sementara permukiman terus didorong mendekat ke badan sungai.
Dalam kedua kasus ini, negara terlihat hadir sangat kuat pada saat tanggap darurat, tetapi lemah dalam tahap pra-bencana.
Lebih dari satu dekade lalu, dalam sejumlah tulisan opini, saya pernah mengingatkan bahwa banjir bukan semata persoalan air, melainkan persoalan hutan, tata ruang, dan nasib kelompok miskin yang selalu menjadi penanggung risiko terakhir. Pesan itu terasa kembali relevan hari ini, ketika banjir dan longsor terus berulang, sementara kerentanan sosial justru semakin mengeras. Yang berubah hanyalah lokasi kejadian; pola persoalannya nyaris tidak bergeser.
Bangkit dari dua lapis kelemahan
Meski demikian, situasi ini tidak harus dibaca secara pesimistis. Justru di tengah krisis berulang inilah terdapat peluang untuk bangkit dari dua lapis kelemahan tersebut. Adaptasi lokal dan kebijakan tata ruang tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Keduanya perlu dijahit dalam satu kerangka pengelolaan risiko yang adil dan berkelanjutan.
Pengetahuan lokal belum hilang; ia hanya terpinggirkan. Warga masih memahami tanda-tanda alam, pola air, dan batas aman ruang hidup. Yang dibutuhkan bukan menggantinya dengan teknologi semata, melainkan mengakuinya sebagai dasar perencanaan. Ketika pengetahuan lokal dijadikan rujukan dalam pemetaan risiko, penetapan zonasi, dan perancangan infrastruktur, kebijakan tata ruang tidak lagi terasa asing atau dipaksakan dari luar.
Sebaliknya, negara memiliki peluang untuk memulihkan wibawanya melalui kebijakan tata ruang yang tegas namun adil. Ketegasan tidak identik dengan kekerasan sosial, melainkan konsistensi. Ketika larangan membangun di kawasan rawan benar-benar ditegakkan, ketika sempadan sungai dipulihkan, dan ketika relokasi dilakukan secara manusiawi, masyarakat akan melihat bahwa kebijakan bukan ancaman, melainkan perlindungan.
Banjir di Sumatera dan longsor di Jawa Barat seharusnya dibaca sebagai peringatan kolektif. Bukan semata soal curah hujan, melainkan soal keberanian menata ulang relasi antara manusia, ruang, dan kekuasaan. Selama tata ruang masih bisa dinegosiasikan atas nama kepentingan jangka pendek dengan kalkulasi ekonomi semata, dan selama kearifan lokal hanya menjadi ornamen budaya, bencana akan terus berulang.
Bangkit dari dua lapis kelemahan berarti berani menegakkan batas ekologis sekaligus mendengar pengetahuan yang hidup di masyarakat. Tanpa itu, yang kita wariskan kepada generasi berikutnya bukan pembangunan, melainkan risiko yang terus menumpuk.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya