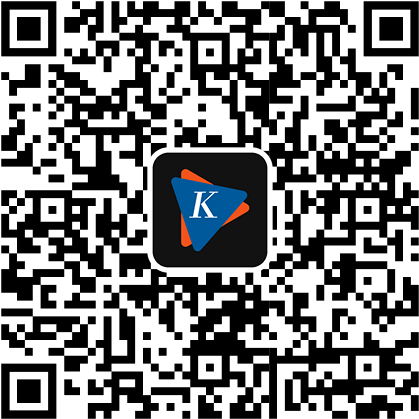Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap krisis iklim, terutama bencana banjir dan panas yang ekstrem.
Selama 2022, Indonesia telah mengalami 3.544 bencana, sekitar 90 persen di antaranya bencana hidrometeorologi.
Sementara menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tren bencana hidrometeorologi Indonesia telah mengalami peningkatan selama 40 tahun terakhir.
Bank Indonesia menganalisis, kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrem mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun.
Oleh karena itu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari mendesak Pemerintah Indonesia harus segera mengambil aksi nyata ambisius.
"Kita masih punya peluang jika kita melakukan aksi iklim yang ambisius. Di antaranya dengan percepatan transisi energi," ujar Adila seperti dikutip Kompas.com, dari laman Greenpeace Indonesia, Rabu (22/3/2023).
Baca juga: Pro Kontra Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk Kesinambungan Ketahanan Energi Nasional
Menurut Adila, bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan krisis iklim itu nyata, dan dampaknya semakin masif.
Mengutip Panel Antar-pemerintah untuk Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (IPCC) yang merilis laporan teranyar AR6 Synthesis Report mengenai situasi iklim terkini, Senin (20/3/2023), disebutkan bahwa krisis iklim yang disebabkan oleh manusia (human-caused climate change) telah terjadi secara cepat.
Bahkan, meningkatkan intensitas dan frekuensi terjadinya cuaca ekstrem di setiap wilayah dunia, di antaranya gelombang panas yang semakin intens, hujan lebat, kekeringan, hingga siklon tropis.
Saat ini, kenaikan temperatur Bumi telah mencapai 1.1°C dan menuju pada kenaikan temperatur global rata-rata pada 2.8°C pada tahun 2100 berdasarkan komitmen negara-negara di dalam Nationally Determined Contributions (NDC).
Angka ini hampir dua kali lipat dari target 1.5°C yang tertuang dalam Paris Agreement, yaitu batas aman bagi Bumi untuk pemanasan global.
“Hal ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan oleh negara-negara belum cukup dan akan membawa dunia menuju climate catastrophe yang lebih parah,” kata Adila.
Namun di sisi lain, AR6 Synthesis Report juga menyatakan masih mungkin untuk mencapai target 1.5°C pada tahun 2100 dengan melakukan segala upaya mitigasi yang ambisius untuk mengurangi emisi sebesar 50 persen pada 2030 dan mencapai nol emisi tahun 2050.
Percepatan transisi energi
Merujuk AR6 Synthesis Report, transisi energi dari energi fosil ke energi matahari dan angin akan menguntungkan.
Harga listrik dari energi terbarukan telah bersaing, bahkan lebih murah, dibandingkan harga listrik dari energi fosil.
Berdasarkan data IPCC, dari 2010 hingga 2019, harga energi matahari turun 85 persen dan energi angin turun 55 persen.
Solusi selanjutnya adalah mengakhiri penggunaan energi fosil secepatnya, yaitu dengan menghentikan pembangunan pembangkit fosil baru dan memensiunkan pembangkit fosil yang ada.
“Dekade ini sangat krusial untuk mempercepat transisi energi dan melakukan mitigasi lainnya sebelum bumi mencapai titik kritis dan mengalami kerugian fatal seperti hilangnya keanekaragaman hayati, kenaikan muka air laut, dan mencairnya es kutub,” desak Adila.
Negara maju harus lebih ambisius membuat kebijakan pengurangan emisi agar target yang diproyeksikan di NDC bisa tercapai.
Selain itu, lembaga finansial global pun perlu berkomitmen lebih tegas untuk tak lagi mendanai industri fosil, seperti batu bara dan turunannya.
Aksi iklim yang lebih ambisius juga mesti dilakukan pemerintah Indonesia. Pada 2020, Indonesia menempati peringkat kelima dalam daftar tujuh negara dengan emisi terbesar dengan total emisi 55 persen dari emisi global.
Namun, target pengurangan gas rumah kaca Indonesia yang tertulis dalam Enhanced NDC masih dinilai highly insufficient atau sangat tidak memadai, dan diprediksi akan membawa kenaikan temperatur hingga 4°C jika semua negara mengadopsi komitmen yang serupa.
Sektor energi, yang diproyeksikan akan menyumbang 58 persen dari total emisi tahun 2023, harus menjadi kunci bagi pemerintah dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Sayangnya, beberapa kebijakan pemerintah seperti Perpu Cipta Kerja, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 112 Tahun 2022 justru masih memberikan ruang dan insentif bagi energi fosil.
Persentase energi terbarukan pun masih rendah, yakni 10.4 persen pada 2022. Padahal, Indonesia harus mencapai target 34 persen energi terbarukan pada 2030, sesuai kesepakatan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JET-P).
Maka dari itu, perlu dipastikan pula pendanaan yang terbatas tersebut dialokasikan untuk mendorong percepatan pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia dan bukan untuk solusi palsu lainnya, seperti nuklir dan gas yang sempat dibicarakan pemerintah.
Pemerintah Indonesia harus mengacu analisis ilmiah IPCC dalam membuat kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Percepatan transisi energi serta menghentikan penggunaan batu bara dan energi fosil lainnya mendesak dilakukan agar Indonesia berada di jalur yang sesuai demi mencapai target 1.5°C yang tertuang dalam Kesepakatan Paris.
Menurut Adila, hal Ini menjadi tahun yang terpenting bagi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legacy dengan membuat komitmen dan aksi iklim yang lebih ambisius menuju Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-28 mendatang.
"Selain itu juga mengimplementasikannya sekarang, menimbang bahwa komitmen iklim Indonesia dalam Enhanced NDC masih dinilai highly insufficient dan akan membawa kenaikan temperatur hingga 4°C atau jauh dari target Paris Agreement,” tuntas Adila.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya