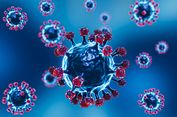JAKARTA, KOMPAS.com – Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), pada akhir November 2025 bukan hanya merenggut hampir 1.000 jiwa dan menenggelamkan ribuan rumah.
Bencana itu juga menyisakan luka senyap yang kerap luput dibahas pada hari-hari awal krisis, yakni keselamatan perempuan.
Lebih dari dua minggu berlalu, sebagian wilayah yang terisolasi. Upaya penanganan pun masih terfokus pada kebutuhan dasar, seperti tenda, makanan, air bersih, layanan kesehatan darurat, dan evakuasi warga.
Namun, di balik hiruk-pikuk penyelamatan, ada risiko yang melekat dan tak kalah genting, yakni kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender.
Situasi tersebut mengingatkan kembali pada pengalaman pascabencana likuefaksi Sulawesi Tengah, khususnya di Sigi, Palu, dan Donggala, pada 2018. Kala itu, minimnya pengawasan, tekanan psikososial, dan terbatasnya layanan membuka ruang terjadinya kekerasan berbasis gender di tengah pengungsian.
Pengalaman itulah yang ditegaskan oleh aktivis kemanusiaan, akademisi, sekaligus Programme Manager Yayasan Kerti Praja (YKP) Dinar Lubis ketika berbincang seusai Talk Show “Perempuan Tangguh, Kita Tangguh – Cerita dari Sulawesi Tengah dan Sekitarnya” di fX Sudirman, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Banyak perempuan kehilangan ruang aman dan kendali terhadap lingkungan sekitarnya,” ujar Dinar.
Baca juga: Perempuan dan Anak Jadi Korban Ganda dalam Bencana Sumatera, Mengapa?
Untuk diketahui, acara yang digagas UN Women PBB itu digelar sebagai bagian dari peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang berlangsung mulai 25 November atau bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember atau bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM).
Perempuan dalam situasi bencana
Menurut Dinar, hari-hari pertama pascabencana adalah periode paling kritis bagi perempuan. Ketika akses kebutuhan dasar terhambat, kecemasan kolektif meningkat.
Selain kehilangan kendali atas lingkungan sekitar, mereka juga kehilangan ruang aman, baik secara fisik maupun psikologis.
Dinar menjelaskan, dalam kondisi bencana, perilaku antisosial lebih mudah muncul, mulai dari konflik antarwarga, penjarahan, hingga kekerasan berbasis gender.
Pelaku memanfaatkan kekacauan dan minimnya pengawasan. Tak ayal, perempuan pun menjadi kelompok yang paling sering tidak terlihat dalam situasi darurat. Padahal, risiko yang mereka hadapi justru meningkat.
Kondisi banjir Sumatera memperlihatkan pola serupa. Banyak fasilitas kesehatan rusak atau tidak berfungsi. Di sisi lain, ibu hamil, pasien penyakit kronis, dan perempuan dengan kebutuhan kesehatan reproduksi (kespro) bergantung pada layanan tersebut.
Bagi perempuan dengan HIV, misalnya, keterlambatan mendapatkan obat dapat menimbulkan dampak serius. Begitu pula ibu hamil yang mendekati waktu persalinan.
“Keterlambatan layanan yang menyangkut kesehatan reproduksi bukan hanya soal medis. Ini juga bisa menjadi bentuk kekerasan struktural yang dampaknya panjang,” ucap Dinar.
Baca juga: RI dan UE Gelar Kampanye Bersama Lawan Kekerasan Digital terhadap Perempuan dan Anak
Pengalaman di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa isolasi dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan. Setelah gempa dan likuefaksi, banyak perempuan harus bertahan di tenda pengungsian tanpa penerangan memadai, tanpa sekat, dan tanpa ruang aman.
Pada masa itu, layanan kesehatan reproduksi baru bisa dihadirkan setelah 45 tenda kespro dan hampir 20 ruang ramah perempuan didirikan.
“Sebelum itu berdiri, banyak perempuan berada dalam situasi penuh ketidakpastian,” kenangnya.
Situasi Sumatera hari ini, menurut Dinar, menunjukkan potensi risiko serupa. Pengungsian padat, akses informasi terbatas, dan mekanisme pelaporan belum berjalan optimal.
Pelaku kekerasan pun sulit diidentifikasi, terlebih karena mereka sering kali bukan orang asing, melainkan individu yang memanfaatkan situasi rentan.
“Ini ancaman sunyi. Tidak terlihat, tetapi selalu hadir,” ujarnya.
Menurut Dinar, regulasi sebenarnya sudah cukup kuat, khususnya dalam Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana.
Beleid itu mewajibkan adanya standar minimal pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (PPKPG) dalam respons bencana, mulai dari layanan 24 jam hingga keberadaan ruang ramah perempuan.
 Proses evakuasi warga di Kampung Umang Isaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, paska terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di kawasan itu, karena hujan berturut-turut tanpa henti pada 25-28 November 2025.
Proses evakuasi warga di Kampung Umang Isaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, paska terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di kawasan itu, karena hujan berturut-turut tanpa henti pada 25-28 November 2025.Namun, tak dapat dimungkiri, implementasi di lapangan kerap “jauh panggang dari api”. Untuk itu, di tengah keterbatasan layanan formal, perempuan sering mengandalkan solidaritas sesama.
Baca juga: UN Women Peringatkan, Kekerasan Digital Berbasis AI Ancam Perempuan
Di beberapa pengungsian, Dinar mencontohkan, perempuan membentuk kelompok kecil untuk saling menjaga dan mengawasi pergerakan anak-anak. Strategi informal ini terbukti efektif meskipun tidak cukup untuk menggantikan mekanisme perlindungan yang ideal.
“Perempuan itu punya ketangguhan,” tegas dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana, itu.
Bangun ruang aman dari hulu
Dinar menuturkan, perlindungan perempuan dalam bencana tak boleh dimulai ketika krisis telah terjadi. Kesiapsiagaan prabencana harus memasukkan perlindungan perempuan sebagai pilar utama, termasuk jalur pelaporan, rute evakuasi, dan mekanisme logistik alternatif.
“Kesiapsiagaan terhadap bencana bukan hanya (cara) punya tenda dan logistik, melainkan juga memastikan ada sistem untuk menjaga perempuan tetap aman,” ujarnya.
Dinas kesehatan di setiap daerah sebenarnya memiliki Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) untuk kondisi darurat, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Namun, tanpa sosialisasi masif, informasi ini tidak banyak diketahui masyarakat. Padahal, nomor layanan, tautan pelaporan, dan kontak bantuan psikososial dapat menyelamatkan nyawa.
“Sering sekali perempuan tidak sadar bahwa apa yang mereka alami adalah kekerasan. Mereka juga tidak tahu harus melapor ke mana,” kata Dinar.
Di sisi lain, akar kerentanan perempuan sering terletak pada struktur sosial. Norma yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus mengalah, keterbatasan pendidikan, dan kecenderungan terlalu percaya kepada orang lain membuat mereka sulit mengenali risiko.
 Aktivis kemanusiaan, akademisi, dan Programme Manager Yayasan Kerti Praja (YKP) Dinar Lubis (dua dari kiri) dalam Talk Show bertajuk Perempuan Tangguh, Kita Tangguh - Cerita dari Sulawesi Tengah dan Sekitarnya di fX Sudirman, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Aktivis kemanusiaan, akademisi, dan Programme Manager Yayasan Kerti Praja (YKP) Dinar Lubis (dua dari kiri) dalam Talk Show bertajuk Perempuan Tangguh, Kita Tangguh - Cerita dari Sulawesi Tengah dan Sekitarnya di fX Sudirman, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Bagi Dinar, pemberdayaan bukan hanya soal mengajarkan keterampilan, melainkan juga membentuk daya kritis.
“Perempuan harus diberi ruang untuk belajar dan berpendapat. Ketika berdaya, mereka lebih siap menghadapi situasi krisis apa pun,” ucap dia.
Di tengah banjir Sumatera dan peringatan 16 HAKTP 2025, Dinar mengajak seluruh pihak untuk melihat kembali makna ruang aman. Ia menegaskan bahwa penguatan sistem tidak cukup jika perempuan tidak diberi ruang untuk berkembang.
“Perempuan harus belajar untuk berdaya. Untuk itu, mereka butuh ruang. Ruang untuk tumbuh, untuk belajar, untuk bersuara,” ujarnya.
Menurut Dinar, peringatan 16 HAKTP seyogianya dapat menjadi refleksi bahwa perlindungan perempuan dalam bencana bukan hanya urusan lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif.
“Bencana banjir Sumatera menunjukkan betapa mudahnya ruang aman itu hilang ketika sistem tidak siap. Karena itu, setiap orang memiliki peran untuk mengembalikannya dengan memastikan perempuan terlihat, terdengar, dan terlindungi, baik di situasi darurat maupun setelahnya,” tegas dia.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya