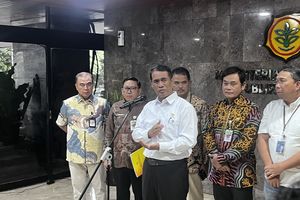Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Sayangnya pemasukkan negara dari sektor kehutanan menurun drastis. Tahun 2022 lalu, Menteri Keuangan RI; Sri Mulyani Indrawati mengaku tak habis pikir bagaimana Indonesia yang memiliki hutan sangat luas, namun sumbangan ke keuangan negara sangatlah kecil.
Sektor kehutanan secara keseluruhan, hanya memberikan setoran dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 5,6 triliun. Padahal, PNBP Indonesia sekarang sudah mencapai hampir Rp 350 triliun.
Lebih jauh, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa setoran PNBP dari hutan kurang masuk akal apabila dibandingkan luas hutan Indonesia yang menguasai daratan Indonesia seluas 120,3 juta ha.
Kegundahan Sri Mulyani masuk akal. Sektor yang tadinya mampu memberikan pemasukan negara sebesar 16 miliar dollar AS per tahun pada era orde baru dan menyumbang devisa kedua sesudah migas, sekarang turun drastis menjadi 375 juta dollar AS per tahun saja.
Menteri Keuangan memprediksi bahwa sebenarnya dominasi PNBP dari basis kayu masih sangat tinggi. Namun PNBP sektor kehutanan sangat kecil disebabkan karena kurangnya pengawasan, penegakan hukum yang lemah, dan kurang komprehensif dan optimalisasi potensi termasuk aset yang dinilai masih menganggur (iddle time).
Konsep menjual hutan/kawasan hutan Indonesia dari pendekatan manfaat tidak langsung datangnya sangat terlambat.
Konsep Multi Usaha Kehutan (MUK) yang digagas oleh para ahli kehutanan dan telah dituangkan dalam PP no. 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, pada dasarnya baik karena mengoptimalkan pemanfaatan lahan kehutanan untuk kegiatan usaha dan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian hutannya.
Namun sayang dalam situasi iklim usaha nasional yang lesu; konsep MUK bagi para pengusaha kehutanan masih sulit diimlementasikan di lapangan. Faktor agroklimat, tenaga kerja dan padat modal menjadi kendala di lapangan.
Konsep menjual karbon melalui perdagangan karbon meskipun menjanjikan dan nilainya sangat tinggi, nampaknya belum menggembirakan apabila melihat data bursa karbon yang dicanangkan Presiden Jokowi bulan September 2023 lalu.
Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan terdapat potensi besar dalam perdagangan karbon yang nilainya berkisar antara 82 miliar dollar AS sampai 100 miliar dollar AS.
Angka ini didapat karena Indonesia 75-80 persen carbon credit dunia dari hutan tropis, mangrove, gambut, rumput laut hingga terumbu karang.
Anggota Komisi Kehutanan DPR, Kamrussamad, memperkirakan potensi ekonomi bursa karbon Indonesia bersumber dari hutan tropis seluas 120,3 juta hektare dapat menyerap emisi karbon 25,18 miliar ton; mangrove seluas 3,31 juta hektare dan menyerap 33 miliar ton serta hutan gambut seluas 7,5 juta hektare yang menyerap 55 miliar ton.
Jika harga karbon Indonesia 5 dollar AS per ton saja, nilai ekonomi perdagangan karbon lewat bursa karbon sangat besar.
Di sisi lain, pengendalian dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam kontribusi nasional yang sudah ditentukan (nationally determined contribution/NDC) membutuhkan anggaran atau dana yang tidak sedikit (cukup besar).
Target Indonesia dalam COP 21 di Paris adalah penurunan emisi GRK 2030, yaitu 29 persen CMI melalui upaya sendiri dan 41 persen CMI melalui bantuan internasional.
Dalam COP 27 di Sharm El-Sheikh, Mesir (2022), target penurunan emisi GRK 2030 menjadi 32,89 persen dengan usaha sendiri dan menjadi 43,2 persen dengan bantuan asing.
Sebagai contoh dalam penurunan GRK di sektor kehutanan yang dijabarkan dalam FOLU (Forest and Other Land Use) Net Sink 2030 yang disusun tahun 2022 lalu, penyerapan GRK ditargetkan 140 juta ton CO2e pada 2030 dan kemudian meningkat menjadi 304 juta ton setara CO2 pada 2050.
Sektor kehutanan hendak menurunkan emisi GRK 17,2 persen dari 2,87 miliar ton perkiraan emisi 2030 dalam skenario penurunan emisi nasional 29 persen.
Untuk itu dalam dokumen Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 disebutkan bahwa total biaya daur hidup yang dibutuhkan untuk kegiatan mitigasi LTS-LCCP menuju net sink untuk periode 2020-2030 diproyeksikan sebesar Rp 204.02 triliun (Rp 18,55 triliun per tahun).
Total kebutuhan biaya tersebut masih jauh di atas ketersediaan dana (defisit) yang dihitung dari proses tagging pendanaan RPJMN untuk kegiatan mitigasi 2020-2024, yakni sebesar Rp 19,61 triliun (Rp 3,92 triliun per tahun) (KLHK 2021).
Jadi, dalam mencapai skenario LCCP yang paling ambisius, dijelaskan kembali oleh Indonesia bahwa terdapat kesenjangan dana untuk kebutuhan aksi mitigasi hingga mencapai Rp 74 triliun (14,8 triliun per tahun).
Belum lagi, kita bicara mengenai kebutuhan penurunan emisi GRK dari sektor lain seperti sektor energi, sektor pertanian, sektor industri dan penggunaan produk (IPPU); sudah barang tentu total defisit pembiayaan penurunan GRK secara keseluruhan akan membengkak lebih besar.
Pembiayaan penurunan GRK yang diharapkan dari perdagangan karbon melalui bursa karbon ternyata belum dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.
Sementara pajak karbon yang menjadi penopang utama dalam penurunan GRK masih akan berlaku tahun 2025, itupun masih wait and see menunggu kondisi politik dan ekonomi Indonesia stabil lebih dahulu.
Dalam urusan memperoleh manfaat tidak langsung dari kawasan hutan yang terlanjur dieksplotasi secara masif nilai ekonominya (manfaat langsungnya), Indonesia menghadapi “buah simalakama”. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya