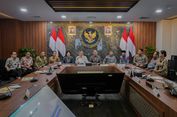Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

BANJIR dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera belakangan ini, memunculkan satu kalimat yang sering terdengar di tengah masyarakat: “Ini aneh.”
Aneh karena di banyak lokasi, termasuk di kawasan hulu DAS Kuranji Kota Padang, tutupan hutan masih tampak hijau.
Tidak terlihat pembalakan besar, tidak ada deforestasi baru, tapi longsor tetap terjadi secara tiba-tiba dan masif.
Pertanyaannya sederhana, sekaligus menyesatkan: jika tidak ada deforestasi, mengapa longsor bisa terjadi?
Pertanyaan ini lahir dari cara pandang lama yang masih dominan di ruang publik. Kita terbiasa memahami bencana sebagai hubungan sebab-akibat yang langsung dan lokal.
Ada longsor, berarti ada hutan yang rusak di tempat itu. Padahal, sains kebumian dan iklim sudah lama menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi bekerja secara akumulatif, lintas wilayah, dan lintas waktu.
Kajian-kajian hidrologi dan geomorfologi menunjukkan bahwa stabilitas lereng sangat dipengaruhi kondisi regional, bukan hanya tutupan lahan setempat.
Laporan FAO dan CIFOR tentang hutan tropis menegaskan bahwa fragmentasi hutan dan alih fungsi lahan di satu kawasan dapat mengubah keseimbangan hidrologi dan atmosfer hingga ratusan kilometer dari lokasi awal.
Baca juga: Imperialisme AS atas Venezuela: Kutukan Sumber Daya hingga Narasi Narkoterorisme
Di Sumatera, deforestasi dan degradasi hutan telah berlangsung selama puluhan tahun. Data menunjukkan bahwa luas hutan primer terus menyusut akibat konversi menjadi perkebunan, infrastruktur, dan kawasan terbangun.
Dampaknya tidak selalu langsung muncul sebagai longsor di lokasi yang ditebang, tetapi terakumulasi dalam bentuk perubahan siklus air, kelembaban tanah, dan pola hujan regional.
Karena itu, tidak adanya deforestasi di satu DAS bukan berarti wilayah tersebut terlepas dari dampak kerusakan hutan di tempat lain.
Hutan dan perannya dalam sistem iklim
Selama ini, hutan sering dipersempit maknanya sebagai daerah resapan air. Padahal, menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), hutan—terutama hutan primer tropis—merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di daratan.
Hilangnya hutan berarti meningkatnya emisi karbon ke atmosfer dan berkurangnya kemampuan alam menyerap gas rumah kaca.
IPCC dalam Assessment Report terbarunya menegaskan bahwa peningkatan suhu global berbanding lurus dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan ekstrem, khususnya di wilayah tropis.
Udara yang lebih hangat mampu menahan lebih banyak uap air, sehingga ketika hujan turun, volumenya menjadi jauh lebih besar dalam waktu singkat.
Dalam kondisi seperti ini, tanah—bahkan yang masih ditutupi vegetasi—dapat mengalami kejenuhan air hingga kehilangan daya ikatnya.
Penelitian geoteknik menunjukkan bahwa longsor sering dipicu bukan oleh hilangnya pohon semata, tetapi oleh curah hujan ekstrem yang melampaui ambang kestabilan lereng.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam berbagai rilisnya menyebutkan bahwa tren hujan ekstrem di Indonesia meningkat dalam dua dekade terakhir.
Di Sumatera, pola hujan ekuatorial yang memang memiliki dua puncak tahunan kini diperkuat oleh variabilitas iklim global, seperti anomali suhu permukaan laut dan pemanasan atmosfer.
Kondisi ini membuat hujan tidak lagi datang secara merata, tetapi dalam bentuk kejadian ekstrem yang singkat dan sangat intens.
Baca juga: Aktor Banjir Kayu di Sumatera
Lereng-lereng yang sebelumnya stabil menjadi rentan, sungai-sungai kecil berubah menjadi aliran bandang, dan kawasan hulu yang tampak hijau pun tidak lagi aman.
Di sinilah krisis iklim bekerja secara nyata di tingkat lokal. Ia tidak menghapus fungsi hutan, tetapi melampaui kemampuan hutan yang tersisa untuk menahan tekanan iklim yang semakin ekstrem.
Mengapa fenomena ini terlihat “aneh”?
Fenomena ini disebut aneh karena cara berpikir kita tertinggal. Kita masih menggunakan kacamata lama untuk membaca alam yang sudah berubah.
Ketika longsor terjadi di kawasan berhutan, kita mengira ada yang tidak masuk akal, padahal yang berubah adalah sistem iklim dan keseimbangan ekologinya.
Para ilmuwan lingkungan menyebut kondisi ini sebagai ecological debt—utang ekologis akibat akumulasi kerusakan lingkungan di masa lalu yang dampaknya baru terasa hari ini. Krisis iklim bertindak sebagai pemicu yang mempercepat dan memperluas dampak utang tersebut.
Jika bencana terus dilihat hanya sebagai persoalan lokal, maka solusi yang diambil akan selalu parsial: normalisasi sungai, tembok penahan, atau relokasi warga. Semua itu penting, tetapi tidak menyentuh akar persoalan.
Hutan harus dipahami sebagai penyangga iklim, bukan sekadar penahan air. Pemulihan hutan tidak bisa lagi dilakukan secara sektoral dan terpisah-pisah, melainkan sebagai bagian dari strategi menghadapi krisis iklim.
Ketika tidak ada deforestasi, tetapi longsor tetap terjadi, itu bukan bukti bahwa hutan tidak lagi berfungsi. Justru itu adalah peringatan bahwa kerusakan hutan—di mana pun terjadi—pada akhirnya akan berdampak ke mana-mana.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya