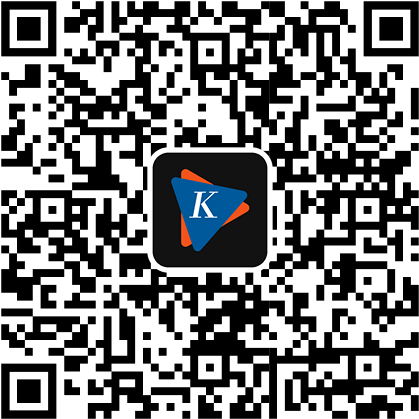Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

DI SATU sisi, negeri ini mengibarkan bendera hijau. Di sisi lain, asap dari cerobong batu bara masih menebal di langit ekonomi nasional.
Itulah paradoks besar Indonesia hari ini—antara komitmen hijau yang kian mengeras di forum dunia dan ketergantungan pada energi fosil yang belum juga surut.
Transisi energi bukan sekadar mengganti sumber listrik. Ia adalah ujian kedaulatan. Pertanyaannya: apakah Indonesia benar-benar sedang menapaki jalan menuju ekonomi hijau, atau justru tersesat di jalan karbon yang baru?
Mimpi hijau, realitas batu bara: Transisi atau transaksi?
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pada 2022.
Target penurunan emisi gas rumah kaca naik dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan upaya sendiri, dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan dukungan pendanaan global.
Di atas kertas, komitmen ini menandai keseriusan Indonesia menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Namun di lapangan, cerita berbeda. Lebih dari 60 persen listrik nasional masih bergantung pada batu bara.
Rencana pensiun dini pembangkit batu bara memang mulai dibahas, tetapi implementasinya berjalan lambat.
Investasi besar tetap mengalir ke sektor fosil, sementara energi terbarukan baru menyumbang sekitar 13 persen dari bauran nasional.
Seperti dua kaki yang melangkah ke arah berbeda, kebijakan energi kita masih mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan.
Pemerintah berada dalam posisi sulit: menjaga agar mesin ekonomi tidak mati, sambil memastikan emisi menurun sesuai janji global.
Dalam pertemuan G20 di Bali pada November 2022, Indonesia mendapat sorotan dunia setelah meluncurkan Just Energy Transition Partnership atau JETP.
Skema pendanaan senilai 20 miliar dolar AS itu disebut sebagai terobosan besar untuk mempercepat transisi energi.
Namun, JETP bukan proyek nasional murni. Ia adalah skema pendanaan internasional yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, dan negara anggota G7 lainnya.
Dana tersebut bukan hibah, melainkan campuran antara pembiayaan lunak, investasi swasta, dan sebagian kecil bantuan teknis.
Dalam dokumen rencana investasi JETP atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), sebagian besar dana baru akan cair setelah proyek memenuhi syarat teknis dan reformasi kebijakan tertentu.
Artinya, Indonesia tidak serta-merta menerima 20 miliar dolar AS. Dana itu datang dengan prasyarat kebijakan dan tata kelola yang harus dinegosiasikan.
Transisi energi di sini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga politik pendanaan global. Jika tidak berhati-hati, Indonesia bisa beralih dari ketergantungan pada batu bara menuju ketergantungan baru pada pinjaman hijau dari luar negeri. Transisi bisa berubah menjadi transaksi.
Kedaulatan fskal dan desentralisasi energi
Transisi energi membutuhkan biaya besar. Bappenas memperkirakan, untuk mencapai net zero emission pada 2060, Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 500 miliar dollar AS di sektor energi saja. Pertanyaannya: dari mana uang sebanyak itu akan datang?
Saat ini, penerimaan negara masih sangat bergantung pada pajak dan royalti energi fosil. Pada 2023, penerimaan dari batu bara mencapai lebih dari Rp 100 triliun.
Jika sumber ini berkurang, sementara pendapatan baru dari pajak karbon belum signifikan, maka ruang fiskal negara bisa menyempit.
Reformasi fiskal hijau menjadi mutlak. Pemerintah perlu mengalihkan sebagian subsidi energi fosil—yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun—ke insentif bagi energi terbarukan dan inovasi rendah karbon. Tanpa keberanian mengubah arah fiskal, transisi hijau hanya akan menjadi slogan.
Namun, kedaulatan energi tidak hanya bergantung pada pusat. Transisi yang berdaulat harus tumbuh dari bawah—dari desa, kabupaten, hingga provinsi.
Langkah menuju ke sana mulai terlihat melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.
Perpres ini memberi kewenangan nyata kepada pemerintah provinsi untuk mengelola penyediaan dan pemanfaatan biomassa, biogas, tenaga surya, angin, air, dan gerakan laut di wilayahnya.
Provinsi juga berhak melaksanakan konservasi energi serta membina dan mengawasi pelaksanaannya.
Kebijakan ini bisa menjadi tonggak penting desentralisasi energi hijau. Daerah tidak lagi sekadar menjadi penerima proyek pusat, tetapi menjadi pelaku langsung yang menyesuaikan transisi energi dengan potensi dan kondisi lokalnya.
Bayangkan jika Papua Barat mengembangkan tenaga air dan bioenergi, Nusa Tenggara memaksimalkan tenaga surya, dan Sulawesi menggerakkan industri nikel hijau berbasis energi bersih.
Namun, regulasi tanpa kapasitas dan pembiayaan akan berakhir sebagai janji kosong. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa transfer fiskal dan investasi publik diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah mengelola proyek energi bersih.
Dengan demikian, transisi energi dapat menjadi sarana pemerataan pembangunan, bukan sekadar proyek hijau di atas kertas.
Kedaulatan fiskal dan desentralisasi energi adalah dua sisi dari kemandirian yang sama: memastikan transisi hijau berpihak pada rakyat, bukan hanya pada investor.
Selain JETP dan desentralisasi energi, Indonesia juga tengah membangun pasar karbon nasional.
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022 menjadi dasar bagi sistem perdagangan karbon dalam negeri.
Melalui Sistem Registri Nasional (SRN) dan IDXCarbon, dunia usaha dapat memperdagangkan sertifikat pengurangan emisi atau carbon credit.
Potensi ekonominya besar, bahkan mencapai miliaran dolar AS per tahun dari sektor kehutanan dan energi.
Namun, di balik peluang itu tersimpan risiko baru. Pasar karbon global masih dikuasai lembaga verifikasi dan sertifikasi dari negara maju.
Standar mereka menentukan nilai jual karbon kita. Jika sistem nasional tidak kuat, Indonesia hanya akan menjadi “penyedia stok” karbon murah bagi pasar internasional.
Kedaulatan ekonomi menuntut kedaulatan data dan verifikasi. Pemerintah harus memastikan sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) dikendalikan oleh lembaga nasional, bukan korporasi asing.
Sebab karbon bukan sekadar angka di bursa; ia adalah wujud dari pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup bangsa.
Sementara itu, politik iklim global semakin keras. Uni Eropa telah memberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mengenakan tarif impor tambahan pada produk dengan jejak emisi tinggi.
Amerika Serikat menggelontorkan subsidi besar bagi industri hijau melalui Inflation Reduction Act. Sementara China memperluas pasar kredit karbon domestiknya.
Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus berdiplomasi agar kebijakan global tidak menjadi hambatan baru bagi ekspor dan pembangunan nasional. Diplomasi iklim kini bukan sekadar forum sopan-santun, melainkan arena perjuangan ekonomi.
Indonesia punya modal besar: hutan tropis, cadangan nikel terbesar di dunia, dan pasar energi yang sedang tumbuh.
Jika dikelola dengan bijak, transisi energi bisa menjadi momentum kemandirian baru. Namun, jika tidak, kita hanya akan menyaksikan episode lama dalam bungkus baru—eksploitasi sumber daya dengan nama “transisi hijau.”
Arah transisi energi Indonesia pada akhirnya akan ditentukan oleh satu hal: keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional.
Bukan sekadar mengejar reputasi hijau di panggung global, tetapi membangun sistem energi yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan.
Kedaulatan energi berarti berani menolak dikte pasar, tapi tetap terbuka terhadap kerja sama yang saling menguntungkan. Ia berarti menjadikan energi bersih bukan sekadar simbol politik, tetapi hak rakyat untuk hidup lebih baik.
Indonesia telah memulai perjalanan panjang menuju masa depan rendah karbon. Jalan itu tidak mudah. Namun, seperti sejarah yang pernah membuktikan, kemandirian sejati selalu lahir dari keberanian menempuh jalan yang sulit—dan kini, jalan itu berwarna hijau.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya