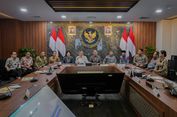JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi persampahan di Indonesia yang masih tercampur dan basah dinilai membuat biaya operasional proyek pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WtE) berbasis proses termal semakin membengkak.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, Pandji Prawisudha, mengatakan teknologi WtE berbasis proses termal pada dasarnya memang dirancang untuk mengolah sampah tercampur, seperti insinerasi yang digunakan secara luas pada tahap awal pengembangan teknologi ini.
“Untuk sampah Indonesia yang tercampur air dan masih basah, dari sisi pengurangan volume memang efektif,” ujar Pandji kepada Kompas.com, Rabu (31/12/2025).
Baca juga: BLDF Serahkan Insinerator untuk Kelola Sampah Residu di Kudus
Ia menjelaskan, sebelum teknologi WtE berkembang seperti sekarang, banyak negara yang kini tergolong maju juga memanfaatkan insinerator untuk menangani sampah tercampur.
Pendekatan tersebut dinilai efektif mengurangi volume sampah dan menekan dampak lingkungan dari penumpukan di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Penumpukan sampah di TPA, kata Pandji, menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO?) dan metana (CH?). Metana yang dihasilkan dari timbunan sampah bahkan memiliki potensi pemanasan global jauh lebih besar dibandingkan CO?.
Gas ini dapat dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) berbasis WtE, meski tetap menghasilkan emisi CO? dan uap air.
“Artinya, baik dibiarkan menumpuk di TPA maupun diolah melalui WtE, emisi gas rumah kaca tetap ada. Kalau ditanya apakah teknologi WtE bisa tanpa emisi GRK, rasanya tidak,” kata Pandji.
Pengendalian Pembakaran
Selain isu emisi, WtE berbasis proses termal juga menghadapi tantangan keekonomian. Untuk menghasilkan gas buang dan residu padat yang relatif aman bagi lingkungan, diperlukan sistem pengendalian pembakaran yang ketat.
Pandji menuturkan, proses pembakaran sampah tidak hanya menghasilkan GRK, tetapi juga polutan berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, fasilitas WtE membutuhkan sistem pengendalian polusi udara yang memadai untuk mengolah abu dan asap hasil pembakaran.
“Kondisi ini membuat investasi dan biaya operasional menjadi tinggi. Apalagi jika sampahnya basah, biasanya dibutuhkan tambahan bahan bakar untuk menjaga suhu pembakaran agar gas buang yang dihasilkan aman dilepas ke lingkungan,” ujarnya.
Dari sisi produksi energi, listrik yang dihasilkan PLTSa juga sangat bergantung pada karakteristik sampah. Sampah basah cenderung memiliki nilai kalor rendah sehingga menghasilkan listrik lebih sedikit dibandingkan sampah kering, terutama yang mengandung plastik atau kertas.
Baca juga: Supian Suri Cari Alternatif Pengganti Mesin Insinerator yang Ditolak Warga Depok
Sebelumnya, Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan **Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov, menilai proyek WtE berpotensi menjadi beban baru bagi pemerintah dan PT PLN (Persero).
Menurut Abra, proyek WtE berisiko meningkatkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, sehingga membebani sistem ketenagalistrikan nasional. Selain itu, investasi WtE yang bernilai triliunan rupiah membutuhkan kepastian pasokan sampah dalam jangka panjang.
“Jaminan pasokan menjadi prasyarat penting. Jangan sampai proyek sudah berjalan tiga atau empat tahun, lalu pasokan sampah di daerah tiba-tiba berkurang,” ujar Abra kepada Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
Ia menambahkan, persoalan WtE tidak hanya terkait pasokan (supply), tetapi juga permintaan (demand) listrik. Meski PLTSa direncanakan dibangun di wilayah dengan timbulan sampah besar dan berkelanjutan, konsumsi listrik di daerah tersebut juga perlu dipastikan.
Dalam kondisi saat ini, PLN masih menghadapi kelebihan pasokan listrik (oversupply), di mana produksi lebih besar dibandingkan konsumsi. Proyek WtE dinilai berpotensi memperparah kondisi tersebut, mengingat konsumsi listrik per kapita di Indonesia masih relatif rendah.
Abra menilai rendahnya permintaan listrik tidak terlepas dari menurunnya kontribusi sektor industri, khususnya manufaktur, terhadap perekonomian nasional. Padahal, sektor industri merupakan salah satu penopang utama peningkatan konsumsi listrik.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya