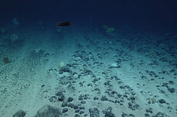CERITA tentang hutan adat dan masyarakat hukum adat (MHA) dengan segala permasalahannya tak habis-habisnya dibahas di negara ini. Namun belum ada penyelesaiannya secara tuntas mau dibawa kemana sebenarnya hutan adat ini.
Harian Kompas secara berseri memuat berita tentang "Hutan Adat" pada 11-18 Desember 2023. Mulai dari judul “Menanti Hutan Adat Diakui”, “Hutan Adat dalam Sengkarut Izin dan Iklim”, "Pengelolaan Hutan Adat Menanti Terobosan”, “Bersetia Menjaga Hutan, Rupiah Pun Mengalir", “Penjaga Hutan yang Terpinggirkan”, “Bibit Harapan di Tanah Batak”.
Semua tulisan tersebut memuat tentang hutan adat dengan masyarakat hukum adat (MHA) yang ingin diakui legalitasnya oleh pemerintah melalui regulasi afirmatif yang mudah, cepat dan sederhana sekaligus untuk memperjuangkan kesejahteraan MHA melalui pengelolaan hutan adatnya.
Dalam tulisan saya di Kolom Kompas.com, 4 Februari 2023, tentang hutan, saya menulis dan mempertanyakan “Hutan Adat Bukan Hutan Negara, Lantas hutan Apa?" yang sampai hari ini belum terjawab dengan tuntas. Kenapa demikian?
Tidak ada hutan adat tanpa masyarakat hukum adat (MHA). Namun sebaliknya, masyarakat hukum adat tidak harus dengan/tanpa hutan adat.
Hutan adat menjadi kawasan hutan yang kontroversial sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara pada 2012.
Sayangnya putusan MK yang membatalkan pasal 5 ayat (2), tidak diikuti dengan perubahan pasal 67 bab masyarakat hukum adat dalam undang-undang (UU) No. 41/1999 tentang kehutanan sehingga proses pengakuan MHA dan hutan adatnya masih sama/tidak berubah, yaitu melalui peraturan daerah yang nampak untuk banyak daerah kabupaten di Indonesia masih sulit diwujudkan realisasi perda semacam ini.
Menurut para pengamat kehutanan, luas kawasan hutan adat di seluruh Indonesia tidak lebih dari 5 persen dari luas kawasan hutan yang 120,3 juta hektare itu.
Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari usulan penetapan hutan adat yang telah memiliki produk hukum, baik peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya luasnya mencapai sekitar 3,66 juta hektare.
UU masyarakat hukum adat yang diharapkan mampu mengakomadasi dan mempermudah pengakuan MHA dan hutan adatnya, belum terdapat tanda-tanda penyelesainnya dan masih jauh dari kenyataan, meskipun tahun 2021, Rancangan UU MHA masuk dalam program legislasi nasional untuk diundangkan.
Rancangan UU MHA bila dikaji dan dipelajari lebih jauh nampaknya juga memberi kesan bahwa pengakuan MHA masih tetap sama. Birokrasinya masih berbelit-belit, panjang dan kurang memihak pada MHA yang secara kultural telah eksis bertahun-tahun dan jumlahnya cukup banyak di Indonesia.
Melihat kenyataan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam turunannya UU Cipta Kerja bidang kehutanan, di Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2021 dan Peraturan Menteri No. 9/2021, berani memasukkan hutan adat (HA) sebagai salah satu skema dari lima skema kegiatan perhutanan sosial selain hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (Hkm), hutan tanaman rakyat (HTR) dan kemitraan kehutanan (KK).
Berdasarkan pembaharuan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), hingga Agustus 2023 telah teregistrasi 1.336 peta wilayah adat yang tersebar di 155 kabupaten/kota dengan luas sekitar 26,9 juta hektare.
Angka ini bertambah 1,8 juta hektare dari data sebelumnya yang dirilis pada Maret 2023 seluas 25,1 juta hektare di 154 kabupaten/kota.
Dari jumlah itu, 219 wilayah adat sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan luas 3,73 juta hektare atau sekitar 13,9 persen. Adapun total hutan adat yang sudah mendapatkan pengakuan sebanyak 123 hutan adat dengan luas 122.648 hektare.
Meskipun hutan adat dengan MHA telah disebut secara tekstual dalam perundangan seperti UU no. 5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, UU no. 5/1967 tentang ketentuan pokok kehutanan, UU no. 41/1999 tentang kehutanan, namun polemik tentang penetapan dan pengakuan hutan adat berkesudahan.
Pangkal pokok masalahnya yang menjadi batu sandungan adalah pengakuan, pengukuhan dan penetapan hutan adat dan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah (Perda) sangat membebani dan memberatkan.
Perda adalah proses keputusan politik yang diambil oleh para elite politik yang duduk di DPRD di tingkat kabupaten/kota yang sarat dengan berbagai kepentingan.
Dalam kasus hutan adat, kepentingan politis dan ekonomis pengakuan hutan lebih banyak ditonjolkan. Akibatnya, upaya penyelenggaraan dan pengakuan MHA berserta wilayah adatnya masih belum optimal.
Terkadang kita dibuat bingung dan heran dengan kebijakan di republik ini, logika terbalik masih digunakan dalam kasus pengakuan hutan adat ini.
Masyarat hukum adat etnis Dayak, misalnya, yang sudah ratusan tahun bermukim di dalam kawasan hutan sebelum Indonesia merdeka dengan wilayah (hutan) adatnya,- tiba giliran hidup di alam kemerdekaan-, untuk mendapatkan pengakuan hutan adatnya secara hukum legal formal sulitnya bukan main.
Hambatan pengakuan hutan adat
Ada beberapa faktor penyebab lambatnya pengukuhan dan penetapan hutan adat dan masyarakat hukum adat selama ini:
Pertama, meski hutan adat bukan negara seperti putusan MK, tidak berarti hutan adat adalah hutan hak atau hutan milik sebagaimana dimaksud pasal 5 UU 41/1999.
Perpu Cipta Kerja bidang kehutanan menegaskan bahwa hutan adat bagian dari perhutanan sosial. Artinya, hutan adat dianggap setara dengan empat skema perhutanan sosial lain yang berada di hutan negara.
Kedua, pengakuan, pengukuhan dan penetapan hutan adat dan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda) sangat membebani dan memberatkan.
Perda adalah proses keputusan politik yang diambil oleh para elite politik yang duduk di DPRD di tingkat kabupaten/kota yang sarat dengan berbagai kepentingan.
Seandainya pengakuan, pengukuhan dan penetapan hutan adat cukup sampai dengan keputusan bupati, maka presiden akan lebih mudah untuk mendorong percepatan pengakuannya.
Ketiga, kebijakan dan regulasi pemerintah dan DPR tentang hutan adat masih bersifat parsial, sektoral dan belum afirmatif (menguatkan) antara satu dengan yang lain.
Menurut Kepala BRWA Kasmita Widodo, komponen di pemerintah pusat yang dianggap paling signifikan perannya dalam mempercepat hutan adat adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Upaya yang perlu dilakukan Kemendagri adalah memonitor capaian pemerintah daerah terhadap implementasi penyelenggaraan pengakuan masyarakat adat.
Sementara KLHK perlu memperluas kerja sama dengan pemda dalam pengakuan hutan adat yang secara pararel mendukung pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya.
Secara spesifik, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan atau mengaktifkan kelembagaan yang memiliki tugas khusus menyelenggarakan pengakuan masyarakat adat serta mengalokasikan anggarannya.
Keempat, RUU Masyarakat Hukum Adat macet di DPR. UU ini kelak jika disahkan, sebaiknya menghapus tahap-tahap yang mempersulit pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat.
Kelima, meskipun hutan adat masuk skema pengelolaan hutan di kawasan hutan, perhutanan sosial menjadi solusi sementara pengakuan masyarakat adat dan hutan adat. Dari 12,7 juta hektare target perhutanan sosial, realisasinya 5,3 juta hektare.
Artinya, masih ada 7,4 juta hektare yang belum tercapai. Tinggal niat dan kemauan politik mengakui masyarakat adat beserta hutan adatnya.
Seharusnya, khusus untuk hutan adat diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah (PP) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (sambil menunggu disahkannya UU MHA, PP ini sebagai turunannya). Tidak semestinya hutan adat masuk dalam skema kegiatan perhutanan sosial.
Perbaikan RUU MHA
Sejak awal berdiri negara ini, sebenarnya masyarakat adat punya tempat tersendiri. Undang-Undang Nomor 5/1967 tentang ketentuan pokok kehutanan, hutan adat diatur secara khusus di pasal 17. Masalahnya, konstitusi ini tak diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah.
Keberpihakan pada investor dalam mengelola hutan membuat masyarakat adat tersisih dari ruang hidup mereka. Ini karena secara regulasi juga ambigu.
Penjelasan pasal 17 UU/5/1967 menyebutkan “…andaikata hak ulayat suatu masyarakat adat digunakan untuk menghalang-halangi rencana umum pemerintah, misalnya, menolak dibukanya hutan untuk proyek-proyek besar, atau untuk kepentingan transmigrasi dan lain sebagainya. Demikian pula tidak bisa dibenarkan apabila hak ulayat dipakai sebagai dalih bagi masyarakat adat membuka hutan secara sewenang-wenang”.
Dengan pengaturan ini tak mengherankan jika banyak meletup konflik tenurial antara masyarakat adat dengan perusahaan pemegang konsesi kehutanan. Konflik terus terjadi hingga hari ini.
Masyarakat adat sedang harap-harap cemas menanti pembahasan RUU Masyarakat Adat yang akan menganulir mekanisme pengakuan hutan dan masyarakat adat.
Mungkin kita perlu melihat bagaimana pemerintah Amerika Serikat menelurkan hak mengelola sumber daya alam bagi suku Navajo Indian, yang tersebar di timur laut Arizona dan wilayah barat laut New Mexico.
Merujuk pengakuan suku Navajo, konstitusi Amerika memiliki kedaulatan mandiri selain kedaulatan pemerintah negara bagian dan federal.
Menariknya, masyarakat adat tidak diwajibkan untuk mematuhi Konstitusi Amerika Serikat dalam membangun model pemerintahan dan menentukan hukum yang berlaku bagi mereka karena mereka merupakan pihak ekstrakonstitutional.
Berkaca dari sejarah Navajo, pemerintah Indonesia bisa memberikan kewenangan lebih luas kepada masyarakat adat dalam eksploitasi sumber daya alam di sekitar ruang hidup mereka.
Selama ini eksploitasi ekonomi dari sumber daya alam di tanah masyarakat adat mengabaikan prinsip partisipatif dan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
Hal ini karena ketiadaan mekanisme yang adil dalam pembagian keuntungan atas hasil eksplorasi atas sumber daya alam yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
Masyarakat adat Navajo memiliki peran penting dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam di wilayah mereka, termasuk melaksanakan kekuasaan untuk mengeluarkan sewa atau izin, dan menetapkan tarif untuk sewa dan royalti, serta berbagai manfaat lain yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam.
Selain itu, mereka memiliki legal standing untuk melakukan proses penuntutan atau gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat apabila ada pelanggaran komitmen keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah masyarakat dan hutan adat Navajo.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya