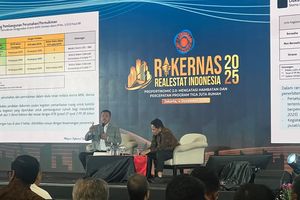BEBERAPA waktu lalu, diskusi online ramai membahas aksi heroik petugas transportasi umum yang membantu penumpang lansia menaiki puluhan anak tangga satu demi satu, perlahan-lahan.
Meskipun aksi tanpa pamrih ini banyak dipuji masyarakat, tapi secara bersamaan mengajak kita mengevaluasi bagaimana ruang publik dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang banyak ragamnya.
Alih-alih jadi membahas mengenai ketidakmampuan fisik yang mencegah untuk menggunakan fasilitas umum, diskusi tersebut memantik dorongan agar fasilitas umum mempertimbangkan aksesibilitas dan inklusivitas.
Desain dan penyesuaian saksama dibutuhkan agar semua orang—terlepas usia dan kemampuan fisik—dapat memanfaatkan fasilitas di ruang publik dengan mudah.
Mengenyahkan hambatan bukan sekadar memberikan akses, tetapi juga merupakan pengakuan hak-hak setiap warga negara untuk menggunakan fasilitas publik dalam melakukan kegiatan seperti bekerja, belajar, atau rekreasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat sekitar 22 juta penduduk Indonesia tergolong penyandang disabilitas—sekitar 5 persen dari total populasi.
Namun, angka ini dicurigai belum mencerminkan kenyataannya. PBB menyoroti adanya potensi pelaporan yang tidak akurat, terutama karena kesenjangan angka yang tampak nyata dibandingkan rata-rata global sebesar 15 persen.
Terlepas dari akurasi data, anggap saja ada 22 juta individu dari berbagai kelompok usia yang menghadapi tantangan setiap hari.
Sebagian besar dari mereka berada di usia produktif, seharusnya memiliki peluang untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi bagi masyarakat. Sayangnya, mereka tetap terpinggirkan, bahkan di kota-kota besar.
Minimnya data akurat tentang disabilitas menyumbang pada rendahnya representasi penyandang disabilitas.
Akibatnya, ketidakpedulian sistemik terhadap mereka terus berlanjut, menjadikan masyarakat dengan disabilitas sebagai kelompok yang terpinggirkan dari kehidupan sosial arus utama.
Pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) mendorong inklusi di berbagai sektor, sejalan dengan prinsip-prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).
Namun, pertanyaan utamanya tetap: bagaimana isu disabilitas dapat diintegrasikan dan diperhatikan dalam bahasan utama di masyarakat jika keberadaannya saja sering diabaikan dalam diskusi DEI?
Disabilitas jadi penonton
Ada dua kesalahpahaman besar yang masih sering muncul terkait disabilitas. Pertama, banyak yang lupa bahwa disabilitas tidak selalu merupakan kondisi bawaan sejak lahir.
Gangguan fisik atau mental bisa terjadi akibat kecelakaan, penyakit, atau yang paling umum, proses penuaan.
Kedua, secara kategori, seseorang dengan disabilitas bukan hanya karena kondisi fisik atau mental yang mereka miliki, tetapi juga karena struktur sosial yang membatasi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.
Bagi penyandangnya, diskriminasi berbasis prasangka terhadap disabilitas, atau yang dikenal dengan ableisme, menjadi kenyataan yang terus-menerus dihadapi.
Prasangka ini, baik yang berakar pada budaya maupun sistem, membuat mereka dipandang sebagai kelompok “lain” yang asing dan rentan diskriminasi.
Pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan, sering kali terabaikan. Hampir 30 persen anak dengan disabilitas tidak memiliki akses ke pendidikan.
Bahkan bagi mereka yang berhasil mengaksesnya, fasilitas yang tersedia sering kali jauh dari memadai.
Isu ini menjadi semakin rumit bagi individu dengan disabilitas tak kasatmata. ADHD dan gangguan spektrum autisme, misalnya, secara langsung memengaruhi cara seseorang berinteraksi dan belajar, meski tidak terlihat secara fisik.
Karena sering diabaikan, mereka kerap tidak memiliki akses ke sumber daya yang memungkinkan partisipasi yang setara.
Akibatnya, kesulitan yang mereka hadapi justru dianggap sebagai tanggung jawab individu semata. Kondisi ini memperkuat akar ableisme dalam masyarakat, meliputi opini publik, perencanaan kota, hingga kurikulum pendidikan.
Hambatan sistemik semacam ini terus mereproduksi ketidakadilan dengan asumsi keliru bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemandirian atau potensi kepemimpinan.
Dengan demikian, disabilitas bukanlah sesuatu yang melekat pada individu, melainkan akibat dari hambatan yang diciptakan oleh sistem.
Penyandang tuli, misalnya, dapat berkomunikasi dengan baik ketika perbedaan bahasa dijembatani, dan anak dengan kesulitan belajar mampu berprestasi jika diberikan metode pembelajaran yang tepat.
Perubahan harus dimulai dengan mengakui keberadaan hambatan tersebut dan mendengarkan suara kelompok disabilitas, seperti yang ditegaskan dalam pendekatan sosial disabilitas (social model of disability).
Inklusi disabilitas bukan soal mengubah individu, melainkan tentang perubahan yang harus terjadi pada masyarakat di seluruh sektor.
Institusi pendidikan tinggi didorong untuk membentuk unit layanan disabilitas sebagai langkah mengatasi hambatan yang dihadapi mahasiswa dengan disabilitas.
Wuri Handayani, dosen Universitas Gadjah Mada sekaligus penerima Alumni UK Social Action Grants dari British Council, menggagas buddy system—sebuah program pendampingan antara mahasiswa disabilitas dan rekan non-disabilitas.
Inisiatif ini tidak hanya menjembatani kesenjangan, tetapi juga mempromosikan inklusi. Melalui program ini, mahasiswa dapat saling belajar dari pengalaman masing-masing, sekaligus menanamkan nilai-nilai masyarakat yang inklusif sejak dini.
Di bidang teknologi, kemajuan era digital sebenarnya membuka peluang besar bagi penyandang disabilitas.
Namun, masih banyak yang tidak memiliki akses memadai maupun keterampilan yang cukup, sehingga ruang digital menjadi terbatas bagi sebagian pihak.
Meski generasi muda sering disebut sebagai digital natives, tingkat literasi digital tetap belum merata, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) di Indonesia.
Untuk menjawab tantangan ini, program Skills for Inclusive Digital Participation kami yang didanai oleh pemerintah Inggris hadir untuk memberdayakan pemuda dengan disabilitas di wilayah Indonesia Timur.
Program ini memberikan pelatihan keterampilan digital, seperti manajemen media sosial dan desain grafis, guna membantu mereka berkembang di dunia yang semakin digital. Selain itu, program ini juga berupaya mendorong inklusi yang lebih luas di sektor teknologi.
Seni dan budaya memegang peranan penting dalam meningkatkan visibilitas kelompok disabilitas.
Di Yogyakarta, sebuah kolektif seni bernama Jogja Disability Arts baru-baru ini menjalankan proyek riset berjudul PRISM bekerja sama dengan DaDaFest UK.
Proyek ini mengeksplorasi kolaborasi seni yang melibatkan penyandang disabilitas. Salah satu metode yang digunakan adalah body mapping yang dimodifikasi—pendekatan kreatif yang menggabungkan seni untuk membantu peserta merefleksikan dan mendefinisikan ulang pengalaman mereka sebagai seniman disabilitas.
Proyek yang banyak melibatkan kaum muda ini tidak hanya memperkuat suara mereka, tetapi juga menampilkan kreativitas yang mampu membangun solidaritas dan menghubungkan komunitas tanpa memandang hambatan.
Inklusi adalah tanggung jawab bersama. Penyandang disabilitas dapat menjadi penggerak perubahan karena partisipasi mereka membawa manfaat besar bagi masyarakat—mendorong keberagaman, menghapus hambatan, dan melahirkan inovasi.
Namun, mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan langkah-langkah berani dan kerja sama yang erat.
Pemerintah dan organisasi perlu mengadopsi social model of disability untuk memastikan aksesibilitas dalam infrastruktur, pendidikan, ruang digital, dan dunia kerja.
Melalui seni dan advokasi, penyandang disabilitas dapat memperkuat suara mereka, memastikan kehadiran mereka di ruang publik, dan memengaruhi kebijakan yang lebih inklusif.
Pada akhirnya, disabilitas bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita—siapa pun bisa mengalaminya, entah karena kecelakaan, penyakit, atau penuaan.
Inilah alasan mengapa membangun lingkungan yang inklusif bukan hanya pilihan, tetapi keharusan.
Dengan infrastruktur yang mendukung, kebijakan yang memberdayakan, dan upaya bersama untuk menghapus stereotip yang merugikan, kita dapat menciptakan masa depan di mana semua orang memiliki tempat dan kesempatan yang sama.
Sebuah masyarakat inklusif adalah masyarakat yang kuat, di mana tidak ada yang tertinggal dan setiap individu dihargai.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya