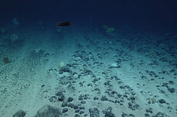SAAT memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia pada 18 September 2023, calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendapatkan pertanyaan menarik dari Dosen UI Suraya Afiff.
Suraya bertanya soal pokok dan penting dalam penguasaan lahan oleh negara yang acap menjadi sumber konflik agraria.
Suraya, tentu saja, mengutip pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Hak menguasai oleh negara inilah yang jadi problem selama Indonesia merdeka, seperti pertanyaan Suraya Afiff.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada sekitar 25.863 desa di dalam dan di sekitar hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga.
Walhi, LSM lingkungan, mencatat 94,8 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh perusahaan atau korporasi. Inilah yang menimbulkan ketimpangan ekonomi.
Di mana hak menguasai oleh negara? Rupanya hak itu didelegasikan kepada korporasi. Masalahnya, delegasi hak itu timpang kepada masyarakat yang justru lebih dulu tinggal di konsesi yang dikemudian diberikan hak pengelolaannya kepada industri.
Di sinilah, pertanyaan Suraya Afiff penting: pasal 33 itu jadi sumber masalah konflik lahan.
Penguasaan lahan di Indonesia pada awal Orde Baru selain menginduk ke UUD 1945 Pasal 33, juga Undang-Undang 5/1960 tentang peraturan dasar pokok agraria dan UU 5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan.
Kedua UU ini mempunyai kedudukan dan posisi yang sejajar dengan tugas yang sama, yakni sama-sama mengatur dan mengurusi lahan, tetapi kewenangannya berbeda.
UU 5/1960 mengatur dan mengurusi lahan di luar kawasan hutan, sedangkan UU 5/1967 mengatur dan mengurusi lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan.
UU 5/1967 diubah menjadi UU 41/1999 tentang kehutanan, sedangkan UU 5/1960 tetap berlaku hingga saat ini.
Sejak UU 5/1967 terbit, luas hutan alam tropika basah yang dimiliki Indonesia secara hukum (de jure) 122 juta hektare atau lebih dari 60 persen dari luas total daratan Indonesia.
Masyarakat adat di areal yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan diakui keberadaannya dalam UU ini, namun regulasi di bawahnya tidak jelas dalam memperlakukannya. Ini juga jadi sumber konflik agraria.
Dalam penjelasan Pasal 17 UU Kehutanan ini disebut bahwa “Selain hukum perundang-undangan, di beberapa tempat di Indonesia masih berlaku hukum adat, antara lain tentang pembukaan hutan penggembalaan ternak, pemburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan.
Dalam pelaksanaan hukum adat setempat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus dijaga jangan sampai terjadi kerusakan hutan, sehingga mengakibatkan manfaat hutan yang lebih penting di bidang produksi dan fungsi lindung daripada hutan akan berkurang adanya.
Demikian pula hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih diakui, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-perundangan lain yang lebih tinggi.
Karena itu tidak dapat dibenarkan jika hak ulayat suatu masyarakat hukum adat setempat digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan rencana umum pemerintah, misalnya: menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk proyek-proyek besar, atau untuk kepentingan transmigrasi dan lain sebagainya.
Demikian pula tidak dibenarkan, apabila hak ulayat dipakai sebagai dalih bagi masyarakat hukum adat setempat untuk membuka hutan secara sewenang-wenang.”
Dalam UU 41/1999 tentang kehutanan, masyarakat adat disebut dengan rinci dan jelas dalam satu bab, satu pasal (67) dan tiga ayat. Dalam pasal 5 ayat (2) UU tersebut, dinyatakan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat.
Mahkamah Konstitusi pada 2012 menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan negara.
Sayangnya, pasal 67 ayat (2) yang mensyaratkan peraturan daerah dalam pengakuan hutan adat tak turut dibatalkan. Sehingga masyarakat adat yang mengajukan hutan adat mesti mendapatkan pengakuan melalui peraturan daerah, yakni kesepakatan antara eksekutif dan legislatif daerah masih mengalami kesulitan.
Dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan PP 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, secara tekstual dan eksplisit akses masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan mendapat ruang dan kesempatan berusaha dalam kawasan hutan melalui kegiatan perhutanan sosial.
Menurut aturan, penguasaan hutan tidak diharamkan atau dilarang dalam kawasan hutan untuk diusahakan dan dipungut hasil hutannya berupa kayu dengan aturan dan persyaratan tertentu.
Pengusahaan hutan inilah yang dipersoalkan Suraya Afiff yang disebut dengan penguasaan lahan hutan untuk diberikan kepada perusahaan atau korporasi hingga saat ini.
Berdasarkan aturan, kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan adalah ilegal kecuali mendapatkan izin.
Dalam PP 28/1985 tentang perlindungan hutan sebagai turunan dari UU 5/1967, Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin Menteri”.
Sekitar 25.863 desa di dalam dan di sekitar hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga yang diungkap Suraya Afiff masuk dalam golongan di luar masyarakat adat.
UU 41/1999 mengatur masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat pemerintah menetapkannya sebagai kawasan hutan.
Dalam PP 6/2007, tentang tata hutan, dan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, pemerintah wajib memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dapat dilakukan melalui kegiatan yang kini dikenal sebagai perhutanan sosial.
Perhutanan sosial adalah bagian dari reforma agraria, selain tanah objek reforma agraria (TORA). Bedanya lahan TORA bisa jadi hak milik, tapi lahannya tak bisa dijual atau diwariskan.
Keduanya adalah implementasi hak menguasai oleh negara yang diatur dalam pasal 33. Masalahnya, delegasi hak kepada industri melalui konsesi dan masyarakat melalui reforma agraria acap timpang sehingga memicu konflik agraria.
Kewenangan Kehutanan
Penguasaan hutan oleh negara berarti negara memberi pemerintah kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatunya terkait dengan hutan. Dari kawasan hingga hasil hutan.
Sayangnya, kewenangan ini tidak diimbangi dengan SDM, regulasi, peralatan dan pendanaan yang memadai sehingga terkesan ala kadarnya. Padahal, SDA hutan 120,3 juta hektare, lebih dari 60 persen menguasai daratan.
Sejak Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah Nomor 32/2004 terbit, kewenangan kehutanan banyak dilimpahkan ke daerah (provinsi/kabupaten/kota).
Kabuapten yang mempunyai potensi SDA hutan besar ramai-ramai membentuk dinas kehutanan untuk menjaring pemasukkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengelola dana bagi hasil (DBH) sektor kehutanan.
Namun para bupati dengan dengan SDA hutan sering salah tafsir. Kasus Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau, 1999-2008, Raja Thamsir Rahman (RTR) menjadi contoh.
Hanya berbekal izin prinsip, Bupati RTR menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan Indragiri Hulu seluas 37.095 hektare.
Padahal, izin usaha perkebunan di kawasan hutan harus dilengkapi izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan izin hak guna usaha (HGU) dari Menteri Agraria/Tata Ruang.
Faktanya, PT. Duta Palma Group dapat mengusahakan kebun sawit sampai kasus terungkap pada Juli 2022. Negara dirugikan Rp 78 triliun.
UU no. 32/2004 direvisi menjadi UU No.23/2014 dan kewenangan kehutanan banyak kembali ditarik ke pusat. Pemerintah kabupaten/kota hanya mengurus Taman Hutan Raya (Tahura).
Banyak bupati jadi tidak peduli masalah kehutanan di daerahnya, seperti kebakaran, perambahan, konflik tenurial, illegal mining, dan illegal logging.
Pemerintah pusat akhirnya kewalahan, khususnya dalam menangani kebun sawit dan pertambangan ilegal. Sawit dalam kawasan hutan mencapai 3,4 juta hektar.
Pengawasan hutan lemah
Perkebunan sawit di kawasan hutan, penambangan ilegal di kawasan hutan, perambahan, hingga pembalakan liar adalah cermin lemahnya pengawasan bidang kehutanan.
Barangkali karena itu PP 23/2021 yang menjadi turunan UU Cipta Kerja menyediakan satu bab khusus tentang pengawasan bidang kehutanan.
Ada 21 pasal (266-277) yang merupakan penjabaran lima pasal UU Cipta Kerja (pasal 61-65) tentang pengawasan kehutanan.
Definisi pengawasan kehutanan adalah mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan.
Menteri atau gubernur melakukan pengawasan kehutanan yang meliputi perizinan berusaha kehutanan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.
Menteri atau gubernur bisa membentuk pejabat fungsional seperti jagawana atau pengawasan kehutanan untuk keperluan itu. Faktanya, pengawasan kehutanan bermasalah karena banyak sebab. Tiga di antaranya adalah:
Pertama, pembagian kewenangan. Menurut UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pengawasan hutan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat dan kewenangannya tidak dilimpahkan provinsi, apalagi kabupaten.
PP 23/2021 menyebut gubernur melakukan pengawasan kehutanan hanya meliputi sub urusan pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Sementara untuk daerah kabupaten/kota, tidak satu pun kewenangan di bidang kehutanan, kecuali mengelola taman hutan raya di wilayahnya.
Dalam ilmu manajemen modern, untuk memperoleh pengawasan yang efektif apabila rentang kendali ada pada dua tingkat di bawahnya. Pemerintah pusat terlalu jauh kewenangannya mengawasi hutan yang ada di tapak.
Kedua, rentang kendali. Menurut PP 62/1998, pemerintah kabupaten bisa mengurus hutan lindung. Kegiatannya berupa pemancangan batas, pemeliharaan batas, mempertahankan luas dan fungsi, pengendalian kebakaran, reboisasi/reforestasi, dan pemanfaatan jasa lingkungan.
Dengan terbitnya UU 23/2014, kewenangan mengurus hutan lindungi mestinya kembali ke pusat lalu diserahkan kepada provinsi sebagaimana manajemen taman hutan raya yang berada di dua kabupaten.
Pengawasan hutan lindung oleh pemerintah kabupaten menjadi titik terlemah. Pemerintah kabupaten memanfaatkan wewenangnya dengan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung untuk tujuan ekonomi.
Masalahnya, ketika ditarik kembali ke pusat, pengawasannya juga sama lemahnya karena rentang kendali jadi jauh dan panjang.
Ketiga, jumlah jagawana. Polisi kehutanan di seluruh Indonesia sekitar 7.000 orang, tidak sebanding dengan luas kawasan hutan 125,2 juta hektare.
Artinya, 1 jagawana menjaga 18.000 hektare kawasan hutan. Idealnya 1 jagawana hanya menjaga 500-1000 hektare. Sehingga jumlah ideal polisi hutan seharusnya 125.000 orang.
Jumlah pengawas kehutanan lebih tidak memadai lagi. Akibatnya, pengawasan hutan menjadi lemah dan okupasi atau penyerobotan kawasan hutan menjadi problem menahun di Indonesia.
Belum lagi jika kita bicarakan sarana dan prasarana untuk mendukung kerja mereka. Konflik tenurial juga acap terjadi pada hutan masyarakat adat yang belum ditetapkan sebagai wilayah adat.
Sengketanya bisa berupa tumpang tindih izin jika ada pemberian konsesi atau luas yang bertambah atau menyempit karena pemerintah tak kunjung menetapkan tata batasnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya