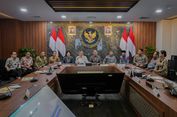JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya regulasi di sektor energi dinilai justru menghambat pengembangan dan inovasi kebijakan energi nasional.
Kondisi yang kerap disebut sebagai hiper-regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan, sehingga arah pengembangan energi nasional menjadi tidak optimal.
Anggota Dewan Energi Nasional, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan hiper-regulasi membatasi ruang gerak para pelaku dan pemangku kepentingan sektor energi untuk berinovasi.
“Banyak pemimpin sektor energi yang akhirnya seperti jalan di tempat. Effort-nya terlalu besar, mau berinovasi ini takut salah, itu takut salah,” ujar Inten dalam acara Outlook Energi Indonesia 2026: Kemandirian, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan, Jumat (9/1/2026).
Baca juga: Fluktuasi Harga Batu Bara Disebut Hantui Indonesia karena Ketergantungan Energi Fosil
Di sisi lain, Inten menilai Indonesia memiliki anugerah sumber daya alam yang melimpah dan potensi energi yang sangat besar.
Komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit, menurut dia, semestinya dapat memberikan kontribusi devisa yang jauh lebih signifikan jika nilai tambahnya ditingkatkan melalui hilirisasi.
Batu bara, misalnya, dapat diolah lebih lanjut melalui proses kimia menjadi syngas, produk substitusi gas alam dan metanol yang dapat dimanfaatkan sebagai biodiesel.
Metanol juga menjadi bahan baku penting untuk berbagai produk turunan kimia, seperti olefin, pupuk, dan aromatik, yang selama ini masih banyak diimpor Indonesia.
Selain itu, coal tar sebagai produk sampingan batu bara dapat diolah menjadi BTX (benzena, toluena, dan xilena) serta naftalen, yang merupakan bahan baku utama industri plastik dan petrokimia.
Sementara itu, kelapa sawit juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan berbasis bio. Inten menyebut, industri kosmetik dan farmasi nasional masih bergantung pada impor bahan baku yang sebenarnya bisa diperoleh dari pengolahan kelapa sawit.
“Sawit mengandung vitamin E yang luar biasa, beta karotinnya tinggi, bahkan bisa menjadi suplemen anti-stunting. Hanya saja, prosesnya memerlukan teknologi yang saat ini belum banyak diterapkan di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Inten, rendahnya pemanfaatan potensi batu bara dan sawit tersebut tidak lepas dari masih terbatasnya peran penelitian dan pengembangan (R&D) di dalam negeri. Ia menilai peran R&D dalam meningkatkan nilai tambah kedua komoditas tersebut masih perlu diperkuat.
Batu bara, kata dia, juga dapat diolah menjadi metanol dan selanjutnya diproses menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG. Saat ini, pemanfaatan DME masih dilakukan secara terbatas dengan skema pencampuran agar kebutuhan investasinya tidak terlalu besar.
Metanol hasil pengolahan batu bara juga digunakan dalam proses produksi biodiesel berbasis kelapa sawit, yang kini menjadi program mandatori pemerintah. Kandungan biodiesel dalam program tersebut terus ditingkatkan secara bertahap, dari B20, B30, hingga saat ini B40.
Baca juga: Wacana Pangkas Produksi Batu Bara Dinilai Harus Percepat Transisi Energi
“Batu bara dan kelapa sawit bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban impor, sekaligus membuka peluang ekspor dan mendorong kemandirian energi nasional,” kata Inten.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya