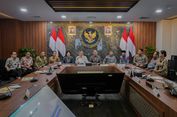KOMPAS.com - Rencana uji coba B50, atau bahan bakar hasil pencampuran solar dan biodiesel dari minyak kelapa sawit sebesar 50 persen, dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2026. Sementara itu, implementasi B50 direncanakan pada semester kedua 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, implementasi B40 atau biodiesel sebesar 40 persen saja dapat mengurangi impor solar hingga lima juta ton pada tahun 2025. Jika persentase biodiesel dinaikkan menjadi 50 persen atau B50, kemungkinan Indonesia bebas dari impor solar.
Baca juga:
- Implementasi B50 Butuh Tambahan Lahan Sawit 2,3 Juta Hektar, 4 Kali Luas Pulau Bali
- POPSI: Naiknya Pungutan Ekspor Sawit untuk B50 Bakal Gerus Pendapatan Petani
Bahlil mengatakan, penghematan devisa sebesar Rp 130,21 triliun dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) mencapai 38,88 juta ton CO2e (karbon dioksida ekuivalen) akibat implementasi B40 pada 2025.
"Jika berhasil maka akan bisa ke B50. Dengan demikian, kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026," ujar Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2025 yang disiarkan secara virtual, Kamis (8/1/2026).
Adakah risiko B50?
Implementasi B50 disebut bersifat trade off
 Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menilai target iklim Indonesia dalam SNDC belum mencerminkan visi energi terbarukan Presiden Prabowo.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menilai target iklim Indonesia dalam SNDC belum mencerminkan visi energi terbarukan Presiden Prabowo.
Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, implementasi B50 memiliki trade off atau situasi yang mengharuskan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan hal lain yang lebih berharga.
Trade off dari implementasi B50 adalah jika tidak bisa meningkatkan produktivitas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), semua yang terkait industri ini akan menjadi korban.
"Kemarin saya mendengar penjelasan Menteri ESDM, saat ada yang tanya (trade off), dia bilang, 'Ya biar negara yang urus deh'. Faktanya, (memproduksi) Fatty Acid Methyl Ester (FAME sebagai produk turunan CPO) itu lebih mahal dari BBM. Apalagi, sekarang harga BBM (bahan bakar minyak) rendah, turun ya. Sementara jika dilihat harga CPO tetap tinggi," jelas Fabby.
Fabby menjelaskannya dalam podcast Outlook Energi Indonesia 2026: Kemandirian, Keterjangkauan, dan Keberlanjutan yang diadakan oleh IESR, Jumat (9/1/2026).
Semakin tinggi campuran biodiesel (FAME) atau naik menjadi 50 persen, akan meningkatkan biayanya. Di sisi lain, selama ini, campuran biodiesel disubsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang bersumber dari pungutan ekspor CPO.
Besaran pungutan BPDPKS tergantung harga CPO. Dana dari pungutan tersebut digunakan untuk membayar selisih harga produksi biodiesel dan riil-nya.
"Sehingga, semua orang bahagia, enggak ada yang dirugikan. Nah, pertanyaannya, apakah dana BPDPKS akan cukup untuk mensubsidi B50, apalagi kandungan FAME-nya lebih tinggi dan harga BBM malah turun?" ucapnya.
Baca juga:
- Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
- Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
 IESR menilai biodiesel B50 memiliki trade off. Jika harga CPO tetap tinggi saat harga minyak global turun, beban subsidi BPDPKS akan meningkat.
IESR menilai biodiesel B50 memiliki trade off. Jika harga CPO tetap tinggi saat harga minyak global turun, beban subsidi BPDPKS akan meningkat.
Selain itu, Amerika Serikat (AS) ingin menurunkan harga minyak dengan meningkatkan produksinya di tingkat global. Kendati terjadi berbagai insidien geopolitik, seperti perang, harga minyak dinilai tidak terlalu terdampak.
"Kita bisa membayangkan beberapa tahun ke depan, itu harga minyak bisa jadi lebih rendah dari sekarang ya. Nah, kita bisa membayangkan kalau sudah ditetapkan B50 ya, terus 2027, harga minyak hanya 50 dollar AS per barel ya," ujar Fabby.
Jika harga CPO tetap tinggi saat harga minyak global justru terus menurun, beban subsidi BPDPKS akan meningkat.
Imbasnya, pemerintah akan terpaksa turun tangan dengan mengucurkan subsidi tambahan, seperti yang terjadi pada tahun 2022.
Hal itu akan berdampak terhadap defisit anggaran negara dan ditambal dengan utang, yang pada gilirannya ditanggung oleh masyarakat melalui pajak. Khususnya, masyarakat kelas menengah dan generasi yang akan datang.
Fabby menilai, secara ekonomi, B50 tidak bermanfaat karena sebenarnya anggarannya bisa dialihkan untuk memberi stimulus untuk pengembangan energi baru terbarukankan (EBT).
"Ini belum program-program lain, seperti rekonstruksi pasca bencana di Sumatera yang biayanya sangat besar. Ini yang perlu menjadi pertimbangan presiden agar tidak atas nama ketahanan energi, tapi ujung-ujungnya membebani APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)," ucapnya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya