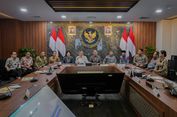Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Oleh Agus Hasan*
KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia resmi memasukkan energi nuklir ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024, yang merupakan dokumen kebijakan jangka panjang sektor kelistrikan.
Dalam rencana ini, pemerintah menargetkan listrik dari energi nuklir mencapai hampir 8 persen dari total kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2060.
Nuklir rencananya akan menjadi pemasok listrik dasar (baseload) untuk memastikan kesetabilan di tengah upaya transisi energi dan pencapaian target nol emisi.
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau untuk mendukung pertumbuhan industri. Tapi pertanyaannya: apakah energi nuklir adalah pilihan yang tepat?
Belajar dari krisis energi Eropa
Tragedi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl 1986 dan Fukushima 2011 menunjukkan dampak fatal dari kegagalan teknis, bencana alam, atau kesalahan manusia dalam mengelola reaktor nuklir.
Baca juga: 20 Persen Listrik Lampung Sudah Berasal dari Energi Terbarukan
Selain risiko keamanan yang tinggi, kritikus juga sering menyoroti modal awal jumbo untuk membangun reaktor nuklir yang mencapai 10 miliar dollar AS atau Rp 163,9 triliun per gigawatt (GW), dengan masa pembangunan sekitar 8-10 tahun.
Namun, krisis energi di Eropa akibat perang Ukraina membuka mata banyak negara soal pentingnya pasokan energi yang stabil. Untuk itu, setiap negara harus berpikir ulang dalam menyusun strategi untuk beralih ke energi yang lebih bersih.
Prancis, misalnya, memutuskan tetap mempertahankan reaktor nuklirnya, yang kini menyuplai hampir 70 persen dari total listrik negara.
Sementara Jerman kukuh memilih menghapus energi nuklir sepenuhnya pada tahun 2023 dan beralih pada energi terbarukan variabel (VRE) seperti tenaga angin dan surya. Sayangnya, produksi listrik dari dua energi ini kurang stabil lantaran bergantung pada kondisi cuaca.
Selama periode “Dunkelflaute" — saat intensitas matahari dan angin sangat rendah — produksi listrik di Jerman turun drastis. Untuk mengatasi kekurangan pasokan, Jerman akhirnya bergantung pada impor listrik dari negara tetangga seperti Prancis dan Swedia, yang mayoritas menggunakan tenaga nuklir.
Ketergantungan ini menyebabkan harga listrik di Jerman melonjak drastis, hingga mencapai 936 Euro/MWh atau Rp 16,6 juta per MWh selama dunkelflaute pada Desember tahun lalu. Angka ini tertinggi dalam 18 tahun terakhir.
Dari Jerman, banyak negara Eropa akhirnya belajar bahwa transisi ke energi terbarukan harus mempertimbangkan keseimbangan antara energi baseload dan VRE. Menurut sejumlah studi, komposisi bauran energi idealnya 60–70 persen energi baseload dan 30–40 persen VRE.
Kebutuhan energi 2050: EBT tidak akan cukup
Dalam pidatonya di pertemuan G20 di Brasil tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia berkomitmen mencapai target nol emisi pada 2050 dengan memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan menggantinya dengan energi baru dan terbarukan (EBT).
Indonesia memiliki potensi EBT yang besar mencapai 3.686 GW, tetapi 93,6 persen di antaranya adalah energi variabel seperti tenaga angin dan surya.
Untuk sumber listrik baseload, Indonesia memiliki panas bumi (geotermal), hidro (air), dan bioenergi dengan potensi kapasitas terpasang masing-masing sebesar 24 GW, 95 GW, dan 57 GW.
Namun, tidak semua pembangkit baseload dapat beroperasi penuh sepanjang waktu. Pembangkit listrik geotermal, misalnya, hanya bisa menghasilkan listrik maksimum 74,3% persen dari kapasitasnya, sedangkan air 41,5 persen, dan bioenergi 67,1 persen.
Pemanfaatan ketiga sumber energi ini juga masih sangat rendah, baru mencapai sekitar 7 persen dari total potensinya. Seandainya seluruh potensi energi terbarukan dimanfaatkan secara maksimal pada 2050, total energi yang dihasilkan hanya sekitar 837 terawatt jam (TWh). Angka ini masih jauh di bawah proyeksi kebutuhan listrik pada tahun tersebut, yang mencapai 2.000 TWh.
Baca juga: Pembentukan Satgas TEH Bisa Percepat Transisi Energi dan Dekarbonisasi
Energi surya dan angin mungkin bisa menjadi sumber energi sepanjang waktu apabila didukung oleh teknologi penyimpanan energi skala besar. Namun, harga baterai penyimpanan yang berskala besar amat mahal dan memiliki risiko keamanan, seperti insiden terbakarnya fasilitas penyimpanan baterai lithium terbesar di dunia, Moss Landing di AS pada Januari lalu.
Kelayakan ekonomis energi nuklir
Secara ekonomi, energi nuklir memiliki biaya awal yang tinggi, tapi bersaing dengan energi terbarukan. Perbandingan kelayakan ekonomi nuklir dan energi terbarukan bisa diukur dengan metode levelized full system cost of electricity (LFSCOE).
Berbeda dengan metode konvensional levelized cost of electricity (LCOE) yang hanya menghitung biaya rata-rata produksi listrik dari suatu pembangkit listrik selama masa operasi, LFSCOE menghitung seluruh biaya tambahan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem listrik, termasuk penyimpanan energi, infrastruktur grid tambahan, serta cadangan daya yang diperlukan untuk menyokong energi terbarukan variabel seperti surya dan angin.
Jika memakai hitungan ini, biaya produksi listrik tenaga nuklir di Jerman adalah 106 dollar AS/MWh atau Rp 1,7 juta/MWh, jauh lebih murah dari tenaga surya yang mencapai 1.548 dollar AS/MWh atau setara Rp 25,3 juta/MWh dan tenaga angin 504 dollar AS/MWh atau Rp 8,2 juta/MWh.
Alternatif bagi Indonesia
Indonesia sedang menghadapi dilema energi yang tidak sederhana: beralih ke energi bersih sambil menjaga kestabilan pasokan.
Energi nuklir, meski berisiko tinggi, menawarkan kapasitas dan kestabilan yang tinggi. Opsi energi ini dipertimbangkan berbagai negara, seperti Prancis dan Swedia.
Lantas apa alternatif terbaik bagi Indonesia?
Pemerintah berencana membangun reaktor nuklir di Pulau Kelasa, Provinsi Bangka Belitung dengan menggandeng perusahaan AS, ThorCon.
Ketimbang langsung membangun pembangkit nuklir skala besar yang risikonya tinggi, Indonesia mungkin bisa mempertimbangkan pendekatan bertahap dengan mengembangkan Small Modular Reactors (SMR) yang lebih fleksibel dan lebih aman.
Indonesia juga perlu menimbang cadangan mineral nuklir yang terbatas, dengan 90.000 ton uranium dan 150.000 ton thorium yang hanya cukup untuk beberapa tahun, sehingga diperlukan kemitraan strategis dengan negara-negara kaya sumber daya seperti Kazakhstan, Kanada, Australia, dan Namibia.
Selain itu, standar keamanan super ketat mutlak diperlukan. Transisi energi tidak bisa ditawar. Namun setiap opsi memiliki tantangan. Jika nuklir menjadi salah satu pilihan, maka semua untung ruginya harus ditimbang dengan sangat cermat.
Baca juga: Setengah Eksekutif Energi Pesimis Capai Nol Emisi pada 2070
*Profesor di Norwegian University of Science and Technology
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya