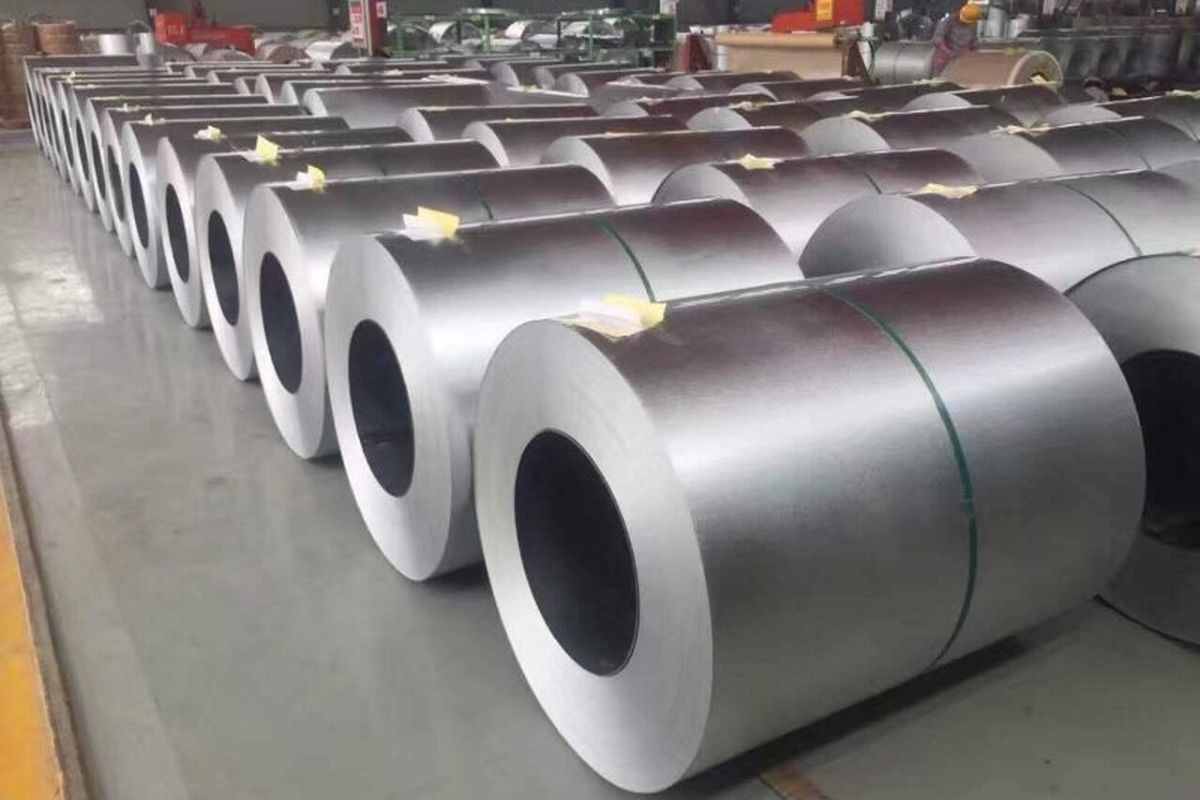
KOMPAS.com - Industri baja berbasis teknologi Blast Furnace–Basic Oxygen Furnace (BF–BOF) terbukti menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (GRK).
Secara ilmiah, teknologi ini menghasilkan emisi sangat tinggi karena bergantung pada batubara sebagai agen reduksi dalam proses produksinya.
Bahkan, emisi yang dihasilkan dari industri baja dengan sistem BF–BOF jauh melampaui teknologi alternatif seperti Direct Reduced Iron–Electric Arc Furnace (DRI–EAF).
Riset terbaru Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bertajuk "Dampak Industri Baja dan Kerentanan Iklim di Kota Cilegon" mengungkap bahwa arah pengembangan industri baja nasional justru masih condong pada penggunaan teknologi BF–BOF.
Padahal, pilihan lain seperti DRI–EAF sudah tersedia dan terbukti lebih ramah lingkungan. Akibatnya, industri baja nasional berisiko memperbesar pelepasan emisi GRK di masa mendatang.
“Arah pengembangan industri baja ke depannya perlu segera dikaji dan diarahkan pada teknologi rendah emisi agar tidak semakin memperburuk krisis iklim, baik secara lokal di Cilegon maupun dalam konteks komitmen iklim nasional Indonesia dan target iklim global,” tulis laporan tersebut.
Baca juga: Indonesia di Tengah Krisis Iklim: Mitra Strategis Dunia dan Pemasok Produk Hijau
Fenomena ini menyingkap paradoks pembangunan di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Di satu sisi, industri baja terus berkembang pesat. Namun di sisi lain, masyarakat sekitar justru menanggung dampak ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang memperbesar kerentanan mereka terhadap krisis iklim dan bencana ekologis.
Klaim pemerintah bahwa industri baja mendorong pertumbuhan ekonomi pun berhadapan dengan kenyataan lapangan. Pertumbuhan industri ini justru memperparah krisis ekologis dan memperlemah kondisi sosial ekonomi warga sekitar. Di tengah krisis iklim global, industri baja menjadi penyumbang emisi GRK besar yang memperburuk ketahanan masyarakat terhadap bencana dan perubahan cuaca ekstrem.
Selain emisi, aktivitas industri baja juga memicu krisis lingkungan yang kompleks—mulai dari polusi udara, pencemaran air tanah dan laut, hingga rusaknya ekosistem di sekitar wilayah pemukiman. Situasi ini diperparah oleh banjir sistemik akibat hilangnya resapan air, reklamasi pesisir, serta degradasi hutan mangrove yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap karbon. Dampak lingkungan tersebut tercermin dari meningkatnya kasus penyakit pernapasan (ISPA) dan gangguan kulit di masyarakat.
Lebih jauh, krisis iklim menghancurkan sumber mata pencaharian warga, khususnya petani dan nelayan, yang menggantungkan hidup di sekitar kawasan industri baja. Hilangnya pekerjaan mempertinggi angka pengangguran dan menimbulkan perubahan sosial yang pelik.
“Tidak dapat dielakkan jika hal tersebut mengakibatkan perubahan sosial yang kompleks. Seperti perubahan dan persaingan gaya hidup, kecemburuan sosial yang berujung konflik, serta maraknya prostitusi dan kawin kontrak. Kondisi ini sangat menghimpit perempuan sebagai entitas yang paling terpinggirkan dan rentan terhadap eksploitasi,” demikian temuan dalam laporan riset tersebut.
Baca juga: Krisis Iklim, Pulau Kecil Tenggelam dan Perlu Mitigasi Berbasis Lokal
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya




















































