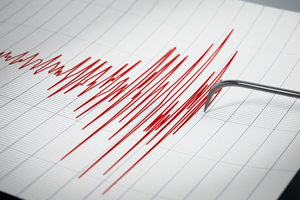JAKARTA, KOMPAS.com - Nikel kini menjadi primadona komoditas dunia. Indonesia tak mau ketinggalan, ikut tren ini dengan gimmick elektrifikasi kendaraan yang digadang-gadang menjadi target besar pembangunan.
Namun, meski dengan alibi ‘pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan’, sejumlah aktivis menilai kekayaan nikel di Indonesia berubah menjadi 'kutukan’.
Menurut Greenpeace Indonesia, nikel menjadi primadona hanya khusus bagi oligarki dan para penguasa, tapi tidak bagi masyarakat adat atau daerah kecil yang sumber dayanya dikeruk.
"Ada orang yang bahkan tidak bisa hidup dan mempertahankan hidupnya karena ruang hidupnya tidak ada lagi. Mereka tidak bisa makan singkong, mereka tidak bisa makan padi, dan sebagainya," ujar Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, saat sesi diskusi film "Kutukan Nikel" di Jakarta, Senin (16/7/2024).
Baca juga: Hilirisasi Nikel Berdampak Serius terhadap Masyarakat Maluku Utara
Ia menjelaskan, di wilayah Indonesia Timur, lebih dari 300 izin usaha pertambangan dengan luasan 3,95 juta hektare atau lebih dari hampir 60 kali luas Jakarta, telah diberikan.
"Dia (pertambangan) juga tidak hanya merusak wilayah hutan yang terbuka itu, tapi juga merusak wilayah pesisir pantai atau bahkan wilayah coastal," imbuh Iqbal.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2011, 28 pulau kecil di Indonesia telah tenggelam, dan 24 pulau kecil terancam hilang.
"Yang kita sesalkan sebenarnya adalah ini peristiwa yang sudah terjadi bertahun-tahun. Maka kutukan sumber daya alam itu disebut juga Dutch Disease atau perilaku Belanda, itu bahasa ilmiah ya, bukan rasis, tapi ilmuwan menyebutnya Dutch Disease, kemarukan mengkeruk sumber daya alam secara berlebih," papar Iqbal.
Potret ketimpangan dan ketidakadilan
Dalam episode kedua "Kutukan Nikel" yang merupakan lanjutan film docu-series The Bloody Nickel episode pertama pada Februari 2024, tergambar jelas perlawanan masyarakat adat terutama di daerah timur Indonesia.
Salah satunya, perjuangan para masyarakat adat Togutil Habeba di Halmahera, Maluku Utara, yang memasang spanduk menentang kehadiran PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Baca juga: Emisi Karbon Baterai Nikel Lebih Tinggi daripada LFP
Ada juga potret ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, yang mengakibatkan puluhan pekerja meninggal.
"Lihat dari film tadi, yang diuntungkan bukan masyarakat yang memiliki lahan, yang diuntungkan itu korporasi sama penguasa. Kita lihat saja bagaimana masyarakat berjuang, mempertahankan lahanan mereka. Jadi (kalau) dibilang keuntungan untuk mereka itu tidaklah, itu jauh dari yang dicita-citakan oleh negara ini," terang Iqbal.
Sementara itu, Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Hema Situmorang mengatakan, ketimpangan dalam industri nikel memang benar adanya.
Hema menuturkan, masyarakat sering diilusi dengan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan, dan seolah mendapat solusi berbagai permasalahan polusi udara hingga iklim, dengan beralih ke kendaraan listrik.
"Dengan beralih ke kendaraan listrik dan sebagainya, (tapi) sekali lagi saya mengajak kawan-kawan harus melihat seluruh rantai prosesnya. Karena yang diuntungkan lagi-lagi para korporasinya," ujar Hema.
Baca juga: 6 Pulau Kecil di Maluku Utara Jadi Konsesi Tambang Nikel
Pasalnya, banyaknya masyarakat adat atau kampung kecil di wilayah timur Indonesia yang merana karena hilangnya tempat hidup mereka, cukup menjadi bukti. Bahwasanya, keuntungan nikel hanya bagi sebagian kelompok kecil saja.
"Kemudian siapa yang paling dirugikan? Kalau kita bicara tentang pulau kecil yang terancam, tenggelam dan sebagainya tadi, tentu saja banyak kontroversi sebagai nelayan dan petani karena berada di wilayah pesisir," tutur Hema.
Tak hanya itu, kecelakaan kerja yang terjadi pada smelter-smelter yang meledak, pelecehan dan kekerasan, dan tingkat deforestasi yang tinggi juga menjadi bukti tak terbantahkan.
"Di kampung, kalau sungainya terdampak, lautnya terdampak, tanahnya terdampak, itu adalah wilayah domestik dari para perempuan yang ada di kampung," jelas Hema.
"Jadi ketika itu semuanya terdampak, pasti urusan segala macam yang ada di rumah itu juga terdampak. Itu rentetannya bisa panjang lagi, KDRT dalam rumah semakin tinggi," sambungnya.
Baca juga: Dorong Hilirisasi, PLN Tambah Daya Listrik Industri Nikel di Kaltim
Adapun peneliti senior dari Sajogyo Institute Eko Cahyono berpendapat, penelitian yang dilakukannya di beberapa desa di Halmahera Tengah dan Kalimantan Timur menunjukkan adanya penggusuran tanpa ganti rugi.
"Ada yang berani melawan kepala desanya, terus bilang, 'Saya harus (dapat) ganti rugi'. Ganti berapa? Paling tinggi untuk yang punya SHM, Rp 20.000 per meter. Kalau yang nggak punya SHM, itu paling banter Rp 3.000 per meter," papar Eko.
Dengan deretan dokumentasi yang ditampilkan dalam "Kutukan Nikel", Iqbal berharap agar film serial dokumenter ini bisa mengetuk kesadaran masyarakat terhadap realita yang terjadi.
"Salah satu tujuan film ini, untuk kita bisa tahu bahwa ada yang enggak baik-baik aja dari semua ini. Film ini harapannya bisa tersebar dalam berbagai dimensi untuk semua orang," pungkasnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya