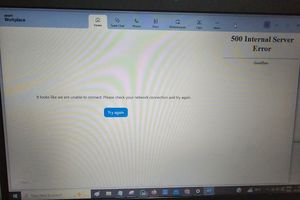ADA pesan sunyi dari timur Indonesia yang sepatutnya kita dengar: Raja Ampat. Gugusan pulau yang kerap disebut sebagai surga dunia itu kini terancam oleh ekspansi tambang nikel.
Padahal, Raja Ampat bukan sekadar wilayah geografis; ia adalah rumah bagi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia sekaligus cermin keharmonisan manusia dan alam.
Sebagai warga yang tinggal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)—yang 96 persen wilayahnya adalah lautan—saya merasa pesan ini sangat relevan.
Kepri dan Raja Ampat memiliki kemiripan: ribuan pulau kecil yang indah, rapuh, dan sering kali hanya dilihat sebagai “sumber daya” yang bisa dieksploitasi, bukan ruang hidup yang harus dijaga.
Kepri merupakan salah satu provinsi dengan garis pantai terpanjang dan jumlah pulau terbanyak di Indonesia: 2.408 pulau besar dan kecil.
Namun, banyak dari pulau-pulau ini kini menghadapi tekanan dari model pembangunan ekstraktif—khususnya tambang pasir, kuarsa, dan bauksit.
Baca juga: Narasi Hijau Palsu: Dampak Nyata Tambang Nikel di Balik Mobil Listrik
WALHI Kepri (2022) mencatat lebih dari 60 lubang tambang ilegal yang menganga di Bintan, belum direklamasi, merusak pesisir, dan menimbulkan abrasi serius.
Aktivitas tambang pasir laut juga menurunkan hasil tangkapan nelayan hingga 30 persen dalam lima tahun terakhir.
Di Pulau Bintan, bahkan beberapa pemukiman pesisir telah terdampak langsung oleh abrasi akibat tambang.
Lebih dari sekadar seruan moral, larangan aktivitas tambang di pulau kecil (rentan) juga telah ditegaskan secara hukum.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 dengan jelas melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 km persegi, apabila merusak daya dukung lingkungan dan mengganggu ekosistem pesisir.
Ketentuan ini berlaku secara nasional dan seharusnya menjadi pijakan semua kepala daerah, termasuk di Kepri.
Kita tahu betul siapa yang seringkali paling diuntungkan: bukan nelayan, bukan masyarakat pulau. Melainkan mereka yang mengantongi izin dan akses kuasa (oligarki).
Potensi wisata yang tergerus
Ironisnya, Kepri justru menyimpan potensi ekonomi jauh lebih berkelanjutan melalui pariwisata bahari.
Sebelum pandemi, Kepri menempati urutan ketiga terbanyak kunjungan wisatawan mancanegara setelah Bali dan Jakarta.
BPS Kepri (2023) mencatat lebih dari 1,1 juta wisman datang ke Kepri, mayoritas tertarik oleh wisata alam, snorkeling, hingga kekayaan budaya maritim.
Pulau-pulau seperti Penyengat, Nikoi, Benan, Senua, dan Berhala sering disebut wisatawan sebagai destinasi dengan daya tarik khas. Namun, banyak dari wilayah ini justru terancam oleh rencana tambang atau stagnasi akibat minimnya infrastruktur antar pulau.
Baca juga: Raja Ampat dan Kutukan Sumber Daya
Menurut studi KKP & UNDP (2022), potensi ekonomi biru Kepri bisa mencapai Rp 6–8 triliun per tahun, terutama dari sektor wisata berkelanjutan, budidaya laut, dan konservasi.
Jumlah ini bahkan melebihi APBD Kepri tahun 2024 yang tercatat sekitar Rp 4 triliun. Jadi, mengapa kita masih terpaku pada pasir dan kuarsa, yang merusak dan tidak terbarukan?
Alih-alih menggali isi perut bumi, Kepri seharusnya memperkuat konektivitas antarwilayah. Letaknya yang strategis di jantung Segitiga Emas Kepri–Singapura–Malaysia adalah peluang besar untuk menjadikan provinsi ini sebagai hub wisata dan logistik kelautan.
Namun, semua itu tak akan berarti jika pulau-pulau rusak dan tak tersambung satu sama lain, baik secara infrastruktur maupun ekosistem.
Investasi pada pelabuhan rakyat, sistem transportasi laut terintegrasi, dan digitalisasi informasi wisata akan memberi manfaat jangka panjang.
Bandingkan itu dengan masa hidup tambang pasir yang hanya beberapa tahun dan menyisakan lubang. Konektivitas adalah kunci investasi dalam pembangunan.
Kita butuh paradigma pembangunan regeneratif, bukan ekstraktif. Tidak semua yang ada di bawah tanah harus diangkat atau ditambang. Sebagian harus tetap tinggal—demi kehidupan jangka panjang.
Mindset pembangunan yang ekstraktif terlalu sering meninggalkan luka dibanding manfaat yang biasanya diperoleh jangka pendek.
Warisan atau jejak kerusakan?
Jika Raja Ampat hari ini bersuara atas nama ekologi dan keberlanjutan, maka Kepulauan Riau (Kepri) seharusnya menjadi pendengar yang bijak. Jangan tunggu giliran untuk menyesal.
Kita sudah melihat cukup banyak jejak tambang yang meninggalkan luka: lubang-lubang menganga, laut yang keruh, kehidupan desa pesisir yang makin sulit dan pelan-pelan ditinggalkan oleh generasi mudanya. Akhirnya hilang harapan.
Baca juga: Tambang Raja Ampat: Dugaan Pelanggaran Hukum Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat
Keserakahan akan selalu memotori pembangunan yang tidak peduli keberlanjutan (sustainability).
Seperti yang pernah dikatakan Mahatma Gandhi, “Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia, tetapi tidak untuk memenuhi keserakahan satu orang”.
Ungkapan ini tepat untuk mengkritik kerakusan eksploitasi tambang atas nama pertumbuhan ekonomi yang tidak peduli lingkungan.
Raja Ampat memberi kita pesan: warisan atau berkah alam tidak selalu harus ditambang. Kadang, menjaga dan merawatnya justru memberi jauh lebih banyak daripada yang bisa dihitung dalam rupiah.
Dan Kepri, dengan semua keindahan dan potensi birunya, memiliki alasan kuat untuk menjadi contoh pembangunan yang sadar laut, sadar ruang, dan sadar masa depan.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya