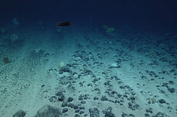Pengawasan hutan lemah
Perkebunan sawit di kawasan hutan, penambangan ilegal di kawasan hutan, perambahan, hingga pembalakan liar adalah cermin lemahnya pengawasan bidang kehutanan.
Barangkali karena itu PP 23/2021 yang menjadi turunan UU Cipta Kerja menyediakan satu bab khusus tentang pengawasan bidang kehutanan.
Ada 21 pasal (266-277) yang merupakan penjabaran lima pasal UU Cipta Kerja (pasal 61-65) tentang pengawasan kehutanan.
Definisi pengawasan kehutanan adalah mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan.
Menteri atau gubernur melakukan pengawasan kehutanan yang meliputi perizinan berusaha kehutanan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.
Menteri atau gubernur bisa membentuk pejabat fungsional seperti jagawana atau pengawasan kehutanan untuk keperluan itu. Faktanya, pengawasan kehutanan bermasalah karena banyak sebab. Tiga di antaranya adalah:
Pertama, pembagian kewenangan. Menurut UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pengawasan hutan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat dan kewenangannya tidak dilimpahkan provinsi, apalagi kabupaten.
PP 23/2021 menyebut gubernur melakukan pengawasan kehutanan hanya meliputi sub urusan pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Sementara untuk daerah kabupaten/kota, tidak satu pun kewenangan di bidang kehutanan, kecuali mengelola taman hutan raya di wilayahnya.
Dalam ilmu manajemen modern, untuk memperoleh pengawasan yang efektif apabila rentang kendali ada pada dua tingkat di bawahnya. Pemerintah pusat terlalu jauh kewenangannya mengawasi hutan yang ada di tapak.
Kedua, rentang kendali. Menurut PP 62/1998, pemerintah kabupaten bisa mengurus hutan lindung. Kegiatannya berupa pemancangan batas, pemeliharaan batas, mempertahankan luas dan fungsi, pengendalian kebakaran, reboisasi/reforestasi, dan pemanfaatan jasa lingkungan.
Dengan terbitnya UU 23/2014, kewenangan mengurus hutan lindungi mestinya kembali ke pusat lalu diserahkan kepada provinsi sebagaimana manajemen taman hutan raya yang berada di dua kabupaten.
Pengawasan hutan lindung oleh pemerintah kabupaten menjadi titik terlemah. Pemerintah kabupaten memanfaatkan wewenangnya dengan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung untuk tujuan ekonomi.
Masalahnya, ketika ditarik kembali ke pusat, pengawasannya juga sama lemahnya karena rentang kendali jadi jauh dan panjang.
Ketiga, jumlah jagawana. Polisi kehutanan di seluruh Indonesia sekitar 7.000 orang, tidak sebanding dengan luas kawasan hutan 125,2 juta hektare.
Artinya, 1 jagawana menjaga 18.000 hektare kawasan hutan. Idealnya 1 jagawana hanya menjaga 500-1000 hektare. Sehingga jumlah ideal polisi hutan seharusnya 125.000 orang.
Jumlah pengawas kehutanan lebih tidak memadai lagi. Akibatnya, pengawasan hutan menjadi lemah dan okupasi atau penyerobotan kawasan hutan menjadi problem menahun di Indonesia.
Belum lagi jika kita bicarakan sarana dan prasarana untuk mendukung kerja mereka. Konflik tenurial juga acap terjadi pada hutan masyarakat adat yang belum ditetapkan sebagai wilayah adat.
Sengketanya bisa berupa tumpang tindih izin jika ada pemberian konsesi atau luas yang bertambah atau menyempit karena pemerintah tak kunjung menetapkan tata batasnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya