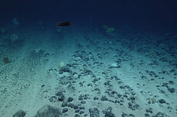Bonanza kayu oleh rezim orde baru selama tiga dekade dimanfaatkan sebagai penggerak roda pembangunan dan merupakan penyumbang devisa negara nomor dua setelah minyak bumi.
Akibatnya hutan alam diekploitasi habis-habisan untuk diekspor kayunya dalam bentuk bahan mentah log (gelondongan). Izin pengusahaan kayu alam dalam bentuk HPH (Hak Pengusahaan Hutan) baik asing maupun domestik terus bertambah.
Devisa negara yang disumbangkan hampir setara dengan minyak bumi, 9 miliar dollar AS per tahun terhadap pendapatan nasional.
Ekses yang timbul dari izin HPH yang tidak terkendali antara lain tidak cermatnya lokasi kawasan yang ditunjuk. Banyak kawasan hutan yang mestinya berfungsi lindung/termasuk hutan gambut masuk dalam wilayah HPH.
Sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) tidak dipatuhi di lapangan karena pengawasan aparat kehutanan setempat lemah. Singkatnya, kaidah kelestarian produksi hutan alam tidak berjalan dengan baik.
Ternyata kelestarian yang dijanjikan dalam regulasi sekelas UU belum terbukti. Jargon tentang timber estate sustainability management hanya terbatas pada diskursus atau wacana saja.
Faktanya, setelah bergantinya rezim dari orde baru ke rezim reformasi, seiring dengan pudarnya kejayaan kayu dari hutan alam Indonesia, muncul masalah baru yang sebenarnya sudah diperhitungkan sebelumnya, yaitu bencana ekologis akibat eksploitasi SDA hutan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) khususnya dari bekas hutan gambut yang menghasilkan bencana asap, selalu muncul setiap tahunnya memasuki musim kemarau seperti sekarang. Pemerintah pusat maupun daerah dibuat kalang kabut untuk mengatasi karhutla.
Konflik tenurial antarwarga dengan korporasi maupun dengan pemerintah terus terjadi dan tak ada habisnya. Hutan "open akses" terlantar akibat ditinggalkan oleh HPH bermasalah atau habis masa kontraknya terus bertambah jumlah dan luasnya. Luas lahan kritis dalam kawasan hutan terus bertambah.
Pemerintahan era reformasi yang sudah berjalan hampir 25 tahun, mencoba memperbaiki sengkarut pengelolaan hutan di Indonesia melalui regulasi dengan menerbitkan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang merupakan revisi dari UU No. 5/1967.
Meski HPH dan HPHH dalam UU 41/1999 berubah menjadi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam (IUPHHK-HA) dan izin usaha pemungutan hasil hutan kayu-hutan alam (IUPHH-HA), dan sistem penebangan diperbaharui dengan metoda RIL (Reducing Impact Logging) dan sistem silvikulturnya ditambah dan disempurnakan dengan silin (silvikultur intensif), namun dalam praktik di lapangan kedua sistem tersebut tidak jauh beda.
Pengawasan kehutanan yang diharapkan mampu untuk meredam dan mengurangi penyimpangan pengelolaan hutan di lapangan kurang berjalan baik dan lemah.
Faktanya, pengawasan kehutanan bermasalah karena banyak sebab. Tiga di antaranya adalah, pertama, urusan pengawasan hutan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat dan kewenangannya tidak dilimpahkan provinsi, apalagi kabupaten.
Kedua, jumlah jagawana (polisi kehutanan) di seluruh Indonesia sekitar 7.000 orang, tidak sebanding dengan luas kawasan hutan 125,2 juta hektare.
Artinya, 1 jagawana menjaga 18.000 hektare kawasan hutan. Idealnya 1 jagawana hanya menjaga 500-1000 hektare. Sehingga jumlah ideal polisi hutan seharusnya 125.000.
Ketiga, pemerintah pusat terlalu jauh kewenangannya mengawasi hutan yang ada di tingkat tapak. Dalam ilmu manajemen modern, untuk memperoleh pengawasan yang efektif apabila rentang kendali ada pada dua tingkat di bawahnya.
Meskipun jargonnya pengelolaan hutan sering diganti-ganti dari timber estate sustainability management menjadi community based forest management dan terakhir sustainable landscape management, namun kebijakan pengelolaan hutan banyak yang bersifat lepas, parsial dan kadang menimbulkan anomali yang sering menimbulkan sengkarut dalam pelaksanaan di tingkat tapak.
Misalnya, kebijakan moratorium pembukaan hutan alam dan gambut. Era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2011, dan kemudian diperpanjang selama empat kali sejak 2011, dan ditetapkan sebagai moratorium permanen pada era Presiden Joko Widodo.
Namun, di sisi lain melalui UU Cipta Kerja dan PP No 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan masih dibuka peluang IUPHHK-HA dalam kawasan hutan produksi pada hutan alam primer.
Portofolio membangun hutan
Sementara, program membangun hutan oleh pemerintah dan korporasi yang telah dilakukan puluhan tahun belum nampak hasilnya secara signifikan.
Puluhan tahun, Indonesia membangun hutan dari sejak adanya Inpres Reboisasi dan Penghijauan 1976 dan berubah menjadi program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) hingga sekarang dengan biaya triliunan rupiah. Namun hasilnya tidak nampak sebagai ekosistem hutan yang utuh.
Apa yang keliru dengan program ini? Selama ini pola dan mekanisme RHL yang dilaksanakan pemerintah sejak era orde baru hingga hari ini, pada prinsipnya tidak berubah sama sekali.
Dalam membangun hutan melalui kegiatan penanaman tanaman hutan (revegetasi) masih menggunakan pola dan mekanisme pemeliharaan tahun pertama (tanaman umur 2 tahun) dan pemeliharaan tahun kedua (tanaman umur 3 tahun).
Selebihnya, mulai tanaman umur 4 tahun dan seterusnya untuk menjadi pohon dewasa yang berumur minimal 15 tahun, pemeliharaan dan proses tumbuh kembangnya tanaman diserahkan sepenuhnya kedalam mekanisme alam tanpa adanya sentuhan manusia lagi.
KLHK masih juga menggunakan paradigma…
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya