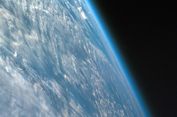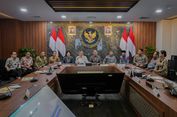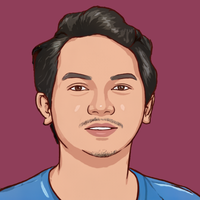
Penulis

KOMPAS.com - Lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai hasil pertemuan para menteri energi negara anggota ASEAN pada akhir September mencerminkan sikap setengah hati dalam transisi energi.
Sebelumnya, para menteri energi negara anggota ASEAN menggelar pertemuan ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ke-42 di Laos.
Dalam kesepakatan bersama 26 September 2024, para menteri energi mendorong pengembangan energi terbarukan namun tetap mempertahankan batu bara dan gas dengan penerapan penangkap dan penyimpang karbon atau CCS.
Baca juga: Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi
IESR menilai, keputusan tersebut membuat ASEAN tampak enggan untuk segera beralih dari energi fosil karena sikapnya yang memilih mengadopsi teknologi CCS.
Lembaga tersebut menilai, fokus ASEAN seharusnya lebih diarahkan pada akselerasi pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang sudah terbukti lebih efektif dan ekonomis.
Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR Arief Rosadi mengatakan, skala keekonomian CCS sampai saat ini masih mahal serta biaya investasi yang tinggi.
Biaya pengoperasian CCS akan semakin mahal jika gas yang diproses memiliki konsentrasi karbon dioksida yang rendah.
Baca juga: Transisi Indonesia Menuju Bioekonomi Sangat Menguntungkan
Selain itu, teknologi CCS belum teruji keandalannya dalam menurunkan emisi, khususnya di Indonesia.
"Negara di kawasan ASEAN sebaiknya memusatkan upayanya untuk mendorong investasi yang tujuannya menurunkan emisi secara signifikan dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, seperti dengan pemanfaatan energi terbarukan," kata Arief dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).
Arief menambahkan, di sisi lain biaya pembangkitan energi terbarukan mengalami tren penurunan sehingga nilai keekonomiannya semakin kompetitif.
"Investasi pada CCS justru akan memperpanjang ketergantungan pada energi fosil dan memperbesar risiko aset mangkrak," ungkap Arief.
Baca juga: Biomassa Jadi Jembatan Penting Menuju Percepatan Transisi Energi
Studi IESR mencatat, CCS memerlukan investasi yang sangat besar yaitu sekitar 3 miliar dollar AS untuk mengurangi 25-33 juta ton karbon dioksida dalam kurun waktu 10-15 tahun.
Jika dibandingkan dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara Indonesia yang mencapai 44,6 gigawatt (GW) pada 2022, penggunaan CCS akan menghabiskan biaya lebih banyak dengan nilai manfaat yang minim dalam upaya mengurangi emisi karbon.
Selain itu, biaya CCS enam kali lebih mahal dibandingkan pembangkitan listrik dibandingkan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) yang didukung oleh teknologi penyimpanan energi.
Koordinator Proyek Transisi Energi Asia Tenggara IESR Agung Marsallindo menyoroti terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses AMEM.
Baca juga: Muhammadiyah Luncurkan Buku Fikih Transisi Energi Berkeadilan, Jadi Panduan Praktis dan Moral
Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik regional yang diambil.
IESR mendorong proses AMEM yang lebih terbuka agar publik dapat terlibat aktif untuk memantau dan memberikan masukan sekaligus menjadi bagian dari transisi energi yang adil dan inklusif.
"Keputusan-keputusan terkait kebijakan energi di tingkat ASEAN juga harus mengikutsertakan lembaga-lembaga masyarakat sipil independen dan tidak berpihak pada kepentingan geopolitik negara manapun," ucap Agung.
Dia menambahkan, setiap keputusan politik akan berdampak pada masyarakat regional. Sehingga partisipasi publik dalam setiap proses sangat penting untuk mengedepankan aspek inklusivitas dan berkeadilan dalam transisi energi.
Baca juga: RI Perlu Tetapkan Target Transisi Energi yang Agresif untuk Raih Pendanaan Maksimal
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya