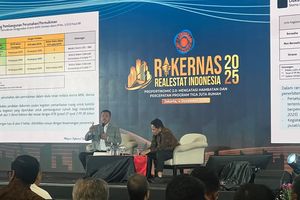BEBERAPA waktu lalu, diskusi online ramai membahas aksi heroik petugas transportasi umum yang membantu penumpang lansia menaiki puluhan anak tangga satu demi satu, perlahan-lahan.
Meskipun aksi tanpa pamrih ini banyak dipuji masyarakat, tapi secara bersamaan mengajak kita mengevaluasi bagaimana ruang publik dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang banyak ragamnya.
Alih-alih jadi membahas mengenai ketidakmampuan fisik yang mencegah untuk menggunakan fasilitas umum, diskusi tersebut memantik dorongan agar fasilitas umum mempertimbangkan aksesibilitas dan inklusivitas.
Desain dan penyesuaian saksama dibutuhkan agar semua orang—terlepas usia dan kemampuan fisik—dapat memanfaatkan fasilitas di ruang publik dengan mudah.
Mengenyahkan hambatan bukan sekadar memberikan akses, tetapi juga merupakan pengakuan hak-hak setiap warga negara untuk menggunakan fasilitas publik dalam melakukan kegiatan seperti bekerja, belajar, atau rekreasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat sekitar 22 juta penduduk Indonesia tergolong penyandang disabilitas—sekitar 5 persen dari total populasi.
Namun, angka ini dicurigai belum mencerminkan kenyataannya. PBB menyoroti adanya potensi pelaporan yang tidak akurat, terutama karena kesenjangan angka yang tampak nyata dibandingkan rata-rata global sebesar 15 persen.
Terlepas dari akurasi data, anggap saja ada 22 juta individu dari berbagai kelompok usia yang menghadapi tantangan setiap hari.
Sebagian besar dari mereka berada di usia produktif, seharusnya memiliki peluang untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi bagi masyarakat. Sayangnya, mereka tetap terpinggirkan, bahkan di kota-kota besar.
Minimnya data akurat tentang disabilitas menyumbang pada rendahnya representasi penyandang disabilitas.
Akibatnya, ketidakpedulian sistemik terhadap mereka terus berlanjut, menjadikan masyarakat dengan disabilitas sebagai kelompok yang terpinggirkan dari kehidupan sosial arus utama.
Pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) mendorong inklusi di berbagai sektor, sejalan dengan prinsip-prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).
Namun, pertanyaan utamanya tetap: bagaimana isu disabilitas dapat diintegrasikan dan diperhatikan dalam bahasan utama di masyarakat jika keberadaannya saja sering diabaikan dalam diskusi DEI?
Disabilitas jadi penonton
Ada dua kesalahpahaman besar yang masih sering muncul terkait disabilitas. Pertama, banyak yang lupa bahwa disabilitas tidak selalu merupakan kondisi bawaan sejak lahir.
Gangguan fisik atau mental bisa terjadi akibat kecelakaan, penyakit, atau yang paling umum, proses penuaan.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya