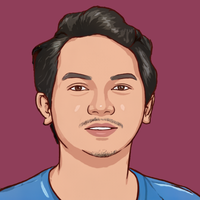KOMPAS.com – Pengelolaan produksi pangan yang lebih adaptif dengan beralih ke sistem yang berkelanjutan dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak krisis iklim di masa mendatang.
Pasalnya, perubahan iklim dan dampak berbagai fenomena alam seperti El Nino telah memengaruhi produktivitas bahan pangan seperti beras.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2015 hingga tahun 2017, produksi padi meningkat dari 69 juta ton ke 81 juta ton gabah kering giling (GKG).
Baca juga: Harga Bahan Pokok Terus Naik, Subtitusi Pangan Konsumen Jadi Kunci
Namun pada 2018, produksi padi menurun cukup drastis yakni 56,54 juta ton hingga mencapai produksi terendahnya pada 2023 sebesar 53,63 juta ton.
Faktor lain yang menyebabkan menurunnya produksi padi selain perubahan iklim yang ekstrem adalah karena berkurangnya luasan lahan sawah yang dipicu oleh alih fungsi lahan.
Dosen dan peneliti pangan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Angga Dwiartama mengkhawatirkan sistem pangan di Indonesia saat ini.
Hal tersebut disampaikan Angga dalam diskusi daring bertajuk "Bahan Pokok Mahal: Pentingnya Keberlanjutan Pangan di Tengah Krisis Iklim" pada Selasa (5/3/2024).
Pasalnya, sistem pangan di Indonesia, khususnya padi, sangat ringkih terhadap guncangan seperti El Nino.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis, Food Estate, dan Diversifikasi Pangan
Menurutnya, berpikir secara business as usual atau konvensional dalam produksi pangan harus ditinggalkan untuk mengantisipasi krisis iklim dan beralih ke arah keberlanjutan pangan.
Ahmad memaparkan tiga rekomendasi utama untuk adaptasi perubahan iklim dalam sektor pertanian padi.
Pertama, pemerintah harus membangun infrastruktur lokal yang sesuai dengan karakteristik sosio-ekologis setiap wilayah. Sentralisasi produksi pertanian harus dihindari, dan infrastruktur yang tangguh harus dibangun sesuai dengan sistem ekologis-sosial setempat.
Kedua, pemerintah harus meningkatkan akses petani gurem terhadap sumber daya pertanian yang mencukupi seperti lahan, air, dan sarana produksi. Pasalnya, petani gurem merupakan mayoritas di Indonesia namun rentan terhadap guncangan
Ketiga, penguatan kapasitas masyarakat perdesaan secara luas melalui praktik adaptasi perubahan iklim.
Baca juga: Bantu Tangani Stunting, 400 Petani Muda di NTT Bangun Ketahanan Pangan
“Masyarakat perdesaan tidak hanya tentang pertanian. Pemahaman yang lebih luas tentang strategi penghidupan dan praktik adaptasi perubahan iklim di perdesaan dapat memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim,” tutur Ahmad dilansir dari siaran pers yang diterima Kompas.com.
Peneliti iklim dari Traction Energy Asia Ahmad Juang Setiawan menyampaikan, krisis iklim juga mengancam produktivitas kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng.
Dampak krisis iklim seperti banjir, kekeringan, dan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memengaruhi produktivitas kelapa sawit melalui beberapa hal seperti pergeseran musim panen, menurunnya kualitas, rusaknya tanaman, hingga potensi kematian tanaman.
Selain krisis iklim, faktor lain yang memengaruhi ketersediaan minyak goreng adalah penggunaan kelapa sawit untuk campuran biodiesel.
Ahmad menuturkan, salah satu cara menuju pangan yang berkelanjutan adalah melihat kembali kearifan lokal dari para petani daerah yang sudah mempunyai mekanisme adaptasi perubahan iklim.
Baca juga: Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Bidang Pangan dari Bapanas
Ia mencontohkan masyarakat adat di Kasepuhan, Banten Selatan, yang memiliki berbagai jenis varietas padi yang sudah disesuaikan dengan berbagai musim.
Selain itu, mereka juga memiliki sistem prediksi awal musim tanam yang cukup baik dengan akurasi yang bahkan bisa menyaingi model prediksi kontemporer.
Menurutnya, hal ini penting untuk memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sistem pertanian dibanding menggunakan satu sistem yang sama untuk semua daerah.
“Pada kenyataannya, setiap daerah memiliki keunikan dan kebutuhan tersendiri yang harus dipertimbangkan,” tutur Ahmad.
Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Supari mengatakan, selama 10 tahun terakhir iklim ekstrem kerap terjadi baik itu El Nino, La Nina, maupun Indian Ocean Dipole (IOD).
Baca juga: Presidium GKIA Luncurkan Buku MPASI Kaya Protein Berbasis Pangan Lokal
Hanya pada 2016, kondisi iklim global mengami fase netral ketika Indonesia mengalami musim kemarau.
Jika La Nina benar akan hadir pada 2024, maka musim kemarau akan terjadi dengan sifat lebih basah.
Hal ini akan baik untuk tanaman padi karena air tercukup, namun mungkin tidak cukup baik untuk tanaman hortikultura seperti sayuran dan cabai karena curah hujan yang berlebihan.
Ia menegaskan pentingnya memahami informasi iklim ekstrem untuk mengurangi risiko dan dampaknya.
Pemerintah, kata Supari, perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi iklim, khususnya bagi para petani yang sebagian besar terdiri dari generasi muda.
“Sehingga mereka melek teknologi informasi dan itu merupakan peluang untuk memberikan pemahaman pada setiap petani untuk mengurangi dampak risiko iklim ekstrem,” ungkapnya.
Baca juga: Pemerintahan Baru Punya PR Bikin Terobosan Energi, Pangan, dan Kesehatan
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya